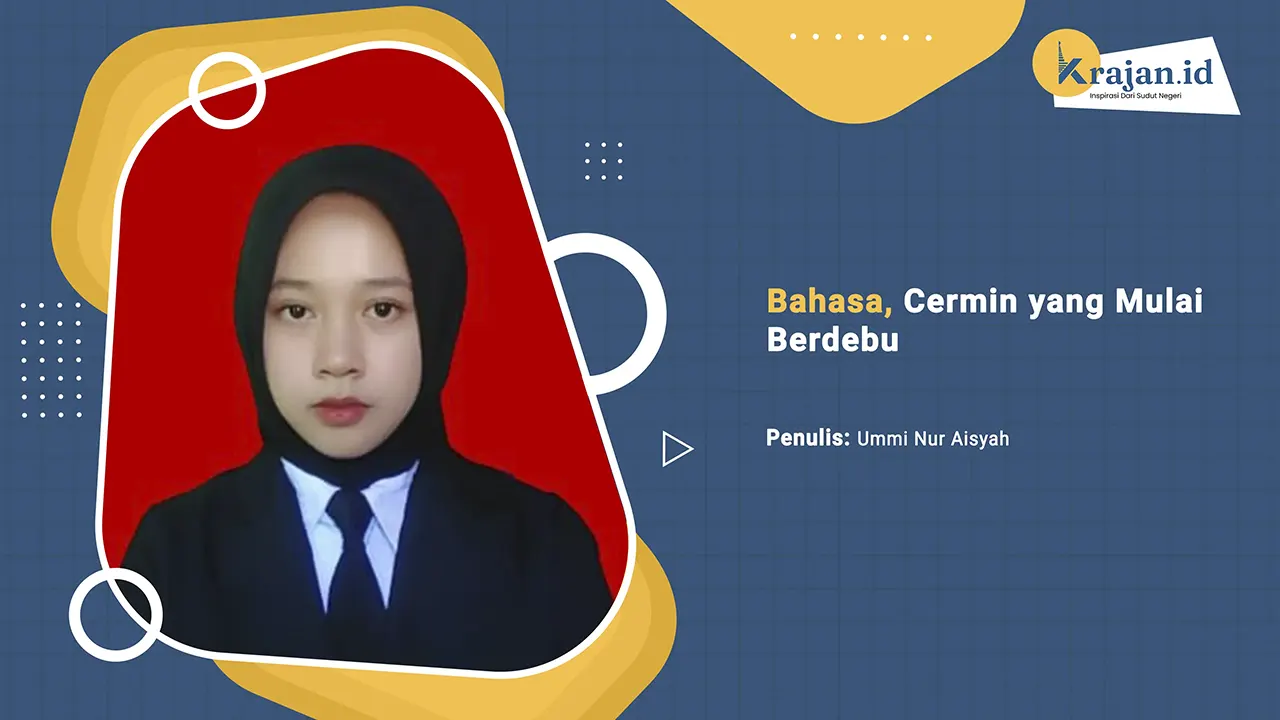Bahasa selalu menjadi penanda paling jujur dari jati diri suatu bangsa. Melalui bahasa, sejarah dituturkan, nilai diwariskan, dan identitas dibentuk. Bahasa Indonesia lahir dari kesadaran kolektif untuk mempersatukan keragaman, sekaligus menjadi alat artikulasi kebudayaan nasional. Namun, dalam kehidupan mahasiswa hari ini, bahasa itu kian tampak kehilangan kejernihannya. Ia masih digunakan, tetapi tidak lagi sepenuhnya disadari maknanya.
Dalam ruang digital yang menjadi habitat utama generasi muda, bahasa Indonesia sering hadir dalam bentuk yang terpecah. Percakapan di grup perkuliahan, media sosial, hingga komunikasi organisasi kampus dipenuhi singkatan, istilah asing, dan campuran bahasa yang digunakan tanpa pertimbangan konteks.
Ungkapan seperti “gw udh kirim tugas”, “nanti di-update”, atau “self-healing dulu” menjadi bahasa sehari-hari. Praktik ini terasa praktis dan modern, tetapi secara perlahan menggeser kesadaran berbahasa yang tertib, jelas, dan bermakna.
Fenomena tersebut tidak sekadar soal pilihan kata. Ia mencerminkan sikap generasi terdidik terhadap bahasa nasionalnya sendiri. Bahasa Indonesia kerap dipersepsikan sebagai bahasa formal yang kaku, hanya layak untuk tugas akademik atau dokumen resmi.
Sementara itu, bahasa asing dan bahasa gaul dianggap lebih ekspresif, lebih cair, dan lebih mencerminkan identitas anak muda. Persepsi inilah yang berbahaya, karena menempatkan bahasa Indonesia pada posisi pinggiran di ruang yang justru paling menentukan pembentukan identitas generasi masa depan.
Di lingkungan kampus, gejala ini tampak nyata. Diskusi kelas sering dipenuhi istilah asing yang sebenarnya memiliki padanan Indonesia yang memadai, tetapi sengaja diabaikan demi kesan intelektual.
Poster kegiatan mahasiswa lebih memilih kata “event” ketimbang “acara”, seolah bahasa Indonesia tidak cukup representatif untuk dunia kreativitas. Media sosial mahasiswa pun menjadi etalase bahasa campuran yang jarang sekali menampilkan bahasa Indonesia yang utuh dan cermat.
Akar persoalan ini tidak berdiri tunggal. Globalisasi digital memang menghadirkan arus bahasa asing yang masif dan nyaris tanpa filter. Namun, persoalan utama terletak pada lemahnya pembinaan sikap berbahasa.
Pendidikan bahasa di sekolah dan perguruan tinggi masih terlalu berfokus pada kaidah dan penilaian, bukan pada pembiasaan dan kecintaan. Bahasa diajarkan sebagai kewajiban akademik, bukan sebagai sarana berpikir dan berekspresi. Akibatnya, mahasiswa memahami aturan, tetapi tidak memiliki ikatan emosional dengan bahasanya sendiri.
Media juga memegang peran krusial. Ketika media arus utama, platform digital, dan figur publik tidak konsisten menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan menarik, pesan yang sampai ke publik menjadi ambigu. Bahasa yang seharusnya menjadi teladan justru diperlakukan sekadarnya. Padahal, media memiliki daya pengaruh besar dalam membentuk selera, kebiasaan, dan standar berbahasa masyarakat.
Meski demikian, menyalahkan perkembangan zaman semata tidak akan membawa perbaikan. Globalisasi bukan ancaman yang harus ditolak, melainkan realitas yang perlu dikelola dengan cerdas. Bahasa Indonesia tidak harus menutup diri dari bahasa lain, tetapi perlu ditempatkan sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Tantangannya bukan memilih antara menjadi modern atau menjaga identitas, melainkan merawat keduanya secara seimbang.
Dalam konteks ini, mahasiswa memiliki posisi strategis. Mereka adalah kelompok terdidik yang aktif di ruang publik, baik fisik maupun digital. Cara mahasiswa menulis, berbicara, dan berkarya akan membentuk wajah bahasa Indonesia ke depan.
Upaya merawat bahasa tidak selalu harus hadir dalam bentuk program besar. Menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dalam diskusi kelas, menyusun pengumuman organisasi dengan diksi yang tepat, atau membuat konten kreatif berbahasa Indonesia yang segar dan relevan merupakan langkah nyata yang berdampak luas.
Organisasi kampus pun dapat berperan sebagai ruang pembiasaan. Lomba debat, penulisan opini, penceritaan digital, hingga podcast berbahasa Indonesia dapat menjadi medium untuk menunjukkan bahwa bahasa nasional mampu tampil modern, kritis, dan menarik.
Pembiasaan semacam ini penting agar bahasa Indonesia tidak lagi dipandang sebagai beban formalitas, melainkan sebagai alat ekspresi intelektual yang lentur dan berwibawa.
Bahasa sejatinya adalah cermin pemikiran. Ketika bahasa digunakan secara serampangan, cara berpikir pun cenderung kabur. Sebaliknya, bahasa yang terawat mencerminkan ketertiban nalar dan kedewasaan sikap.
Di ruang kelas, pilihan kata menunjukkan ketajaman analisis. Di organisasi, bahasa mencerminkan etika dan kepemimpinan. Di media sosial, bahasa membentuk citra diri sekaligus warisan budaya yang ditinggalkan.
Merawat bahasa berarti merawat jati diri. Bahasa Indonesia yang hidup dan jernih mampu menjembatani perbedaan, mendorong dialog yang sehat, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa. Mahasiswa yang mencintai bahasanya tidak sekadar menulis untuk menyampaikan pesan, tetapi menyusun gagasan, merangkai pemikiran, dan menegaskan identitas melalui kata.
Sudah waktunya bahasa Indonesia tidak lagi diperlakukan sebagai simbol seremonial belaka. Di tengah derasnya arus global, bahasa nasional justru dapat menjadi jangkar yang menjaga generasi muda tetap berpijak pada akar budayanya. Dengan kesadaran kolektif, kejernihan bahasa dapat dipulihkan, sehingga cermin itu kembali memantulkan wajah bangsa yang cerdas, kritis, dan percaya diri pada identitasnya sendiri.