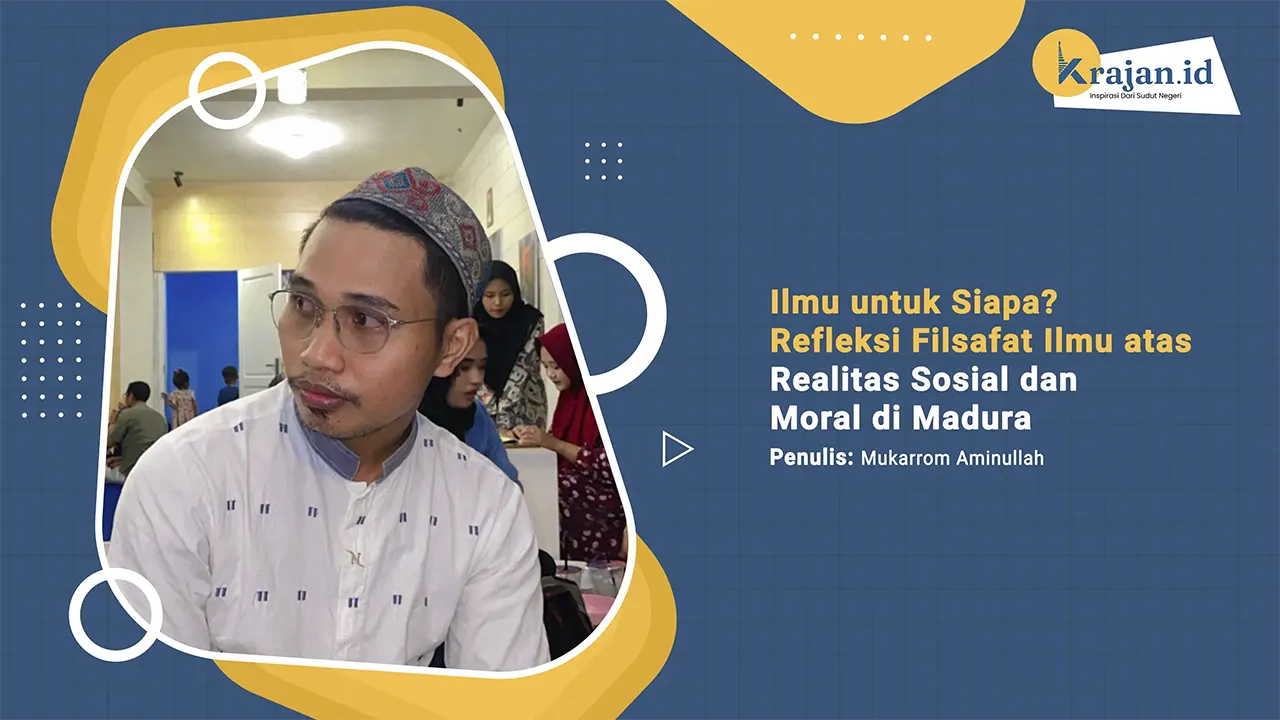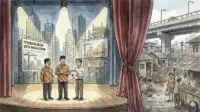Selama bertahun-tahun, ilmu pengetahuan sering dipersepsikan sebagai entitas netral, bebas nilai, dan berdiri di atas segala kepentingan sosial. Namun, dalam realitas sosial seperti di Madura, sebuah wilayah dengan identitas budaya yang kuat, sistem nilai moral khas, serta struktur sosial yang unik, ilmu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan moral masyarakatnya. Ilmu hadir, tumbuh, dan seharusnya memberi kontribusi nyata bagi kehidupan bersama. Maka, muncul pertanyaan mendasar: ilmu untuk siapa?
Pertanyaan ini bukan sekadar retoris. Ia adalah gugatan filosofis yang mengajak kita menelaah: apakah ilmu hanya melayani pasar dan kekuasaan, ataukah berpihak pada keadilan sosial dan nilai-nilai lokal? Dalam konteks Madura, bagaimana ilmu berhadapan dengan realitas masyarakat dan nilai-nilai moralnya?
Pandangan positivistik dalam filsafat ilmu yang melihat ilmu sebagai fakta objektif semata sudah banyak ditinggalkan. Tokoh seperti Paul Feyerabend menolak keabsahan hanya satu metode ilmiah tunggal, dan sebaliknya mendorong pendekatan kontekstual.
Pendekatan semacam ini sangat relevan bagi masyarakat seperti Madura. Ilmu tidak lagi dimonopoli oleh laboratorium atau kampus elite, tetapi harus juga dimiliki oleh masyarakat yang mengalami kehidupan secara langsung.
Ilmu yang bertanggung jawab secara sosial harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Di Madura, tantangan seperti kemiskinan struktural, konflik agraria, dominasi simbolik dan sosial oleh para kiai, serta persoalan modernitas seperti radikalisme dan pergeseran nilai, menuntut kehadiran ilmu yang berpihak. Apakah hasil riset para akademisi telah menjawab persoalan-persoalan ini? Atau justru hanya menjadi alat untuk mengejar angka kredit dan prestise institusi?
Nilai-nilai lokal seperti kehormatan, harga diri keluarga, solidaritas kekerabatan (bhâppâ, bâbbhu, guruh, rato), serta religiositas Islam tradisional, merupakan fondasi moral masyarakat Madura. Ilmu yang berkembang di wilayah ini tidak bisa mengabaikan nilai-nilai tersebut.
Ia bahkan harus berjalan beriringan dan bersinergi dengan moralitas lokal. Namun kenyataannya, banyak pendekatan ilmiah yang tidak peka terhadap budaya lokal. Riset sosial kerap menyederhanakan realitas Madura ke dalam kategori “konflik” atau “kekerasan,” tanpa memahami kompleksitas nilai yang ada. Ini adalah bentuk kolonialisasi epistemik yang halus—ketika ilmu menjadi alat pembacaan yang tidak adil terhadap masyarakat lokal.
Sebagaimana ditegaskan Jürgen Habermas, ilmu seharusnya bukan hanya menjelaskan, tetapi membebaskan. Maka, membangun ilmu di Madura tidak cukup hanya dengan metode ilmiah standar, melainkan perlu pendekatan transdisipliner yang memadukan sains, nilai, dan kearifan lokal.
Pertanyaan “ilmu untuk siapa?” juga menyiratkan persoalan kekuasaan. Michel Foucault mengingatkan bahwa ilmu bukan semata produk rasionalitas netral, tetapi kerap menjadi instrumen kuasa—mengatur dan mendisiplinkan masyarakat.
Di Madura, kita menyaksikan bagaimana pengetahuan tertentu dilegitimasi, sementara pengetahuan rakyat sering diabaikan. Misalnya, dalam pertanian dan perikanan, teknologi modern kerap dipaksakan masuk tanpa memperhitungkan pengetahuan lokal petani atau nelayan. Ini menimbulkan keterasingan masyarakat terhadap ilmu dan menjauhkan mereka dari proses pembangunan.
Pendekatan postkolonial dalam filsafat ilmu menuntut adanya keadilan epistemik. Ilmu tidak bisa bersifat eksklusif, tetapi harus memberi ruang bagi berbagai cara memahami dunia. Dalam hal ini, pengetahuan lokal harus diberi tempat yang setara dengan sains modern.
Madura sebenarnya memiliki sumber daya manusia dan warisan keilmuan yang kuat, terutama melalui lembaga pesantren dan tradisi keulamaan. Namun, hubungan antara ilmu formal di universitas dan pengetahuan tradisional di pesantren belum terjalin secara harmonis.
Dikotomi antara ilmuwan dan kiai, antara modern dan tradisional, masih cukup kentara. Ditambah lagi, akses terhadap pendidikan tinggi masih belum merata. Banyak pemuda Madura yang cerdas namun tidak mampu melanjutkan pendidikan karena kendala ekonomi dan sosial.
Ilmu sering kali dijadikan jalan keluar dari kemiskinan—sekolah tinggi untuk merantau dan bekerja di kota atau luar negeri. Tapi di sinilah letak ironinya: ilmu berubah menjadi jalan pelarian, bukan jalan pulang. Ilmu tidak semestinya hanya melahirkan individu yang sukses secara ekonomi, melainkan juga insan yang bertanggung jawab terhadap tanah kelahiran dan masyarakatnya.
Filsafat ilmu mengajarkan bahwa pertanyaan paling penting bukan “apa yang diketahui?”, tetapi “untuk siapa pengetahuan itu diperjuangkan?” Jika jawabannya bukan untuk rakyat, bukan untuk keadilan, dan bukan untuk kehidupan yang lebih bermartabat, maka ilmu itu telah kehilangan arah.
Kini saatnya kita membangun ilmu yang berpijak pada bumi Madura—menyerap nilai-nilainya, mengakui kompleksitas sosialnya, dan mengabdi bagi kemanusiaan.