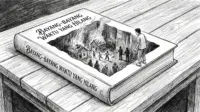Kerusakan lingkungan hidup mulai dari polusi udara, pencemaran air, perusakan hutan, hingga degradasi lahan bukan lagi sekadar masalah teknis atau persoalan ekologis semata. Ia telah menjelma menjadi isu hak asasi manusia sekaligus keadilan sosial. Ketika masyarakat tidak lagi bisa menghirup udara bersih atau kesulitan mendapatkan air minum yang layak, hak-hak dasar mereka pun terampas.
Di Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara tegas dijamin dalam konstitusi. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Lebih jauh, Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kedua pasal ini menegaskan bahwa konstitusi menempatkan lingkungan hidup sebagai aspek fundamental dalam penyelenggaraan negara serta kesejahteraan rakyat.
Sayangnya, kenyataan di lapangan kerap jauh dari amanat konstitusi. Penurunan kualitas lingkungan masih terus terjadi, sementara penegakan hukum lingkungan sering kali lemah atau bahkan mandek.
Data UNICEF menunjukkan hampir 70 persen dari 20.000 sumber air minum di Indonesia telah terkontaminasi limbah tinja. Bahkan, pada 2024 lebih dari 11.000 desa dilaporkan mengalami pencemaran air, dengan mayoritas kasus terjadi di Pulau Jawa.
Dari fakta tersebut, jelas bahwa hak konstitusional atas lingkungan hidup sehat belum sepenuhnya terlindungi. Karena itu, penguatan penegakan hukum menjadi kebutuhan mendesak agar keadilan ekologis tidak hanya berhenti sebagai jargon, tetapi benar-benar bisa dirasakan seluruh warga negara.
Lingkungan Hidup sebagai Hak Konstitusional
Menjadikan lingkungan hidup sebagai hak konstitusional berarti memastikan perlindungan lingkungan tidak dipandang sekadar urusan teknis birokrasi, melainkan kewajiban negara untuk menjamin hak warganya. Dalam kerangka hak asasi manusia (HAM), akses terhadap lingkungan yang sehat berkaitan erat dengan hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas kesejahteraan.
Komnas HAM telah menegaskan bahwa negara memiliki tiga kewajiban utama: menghormati, memenuhi, dan melindungi hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
UU tersebut memuat asas tanggung jawab negara (state responsibility) yang meliputi:
- Menjamin pemanfaatan sumber daya alam memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- Menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- Mencegah kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Dengan demikian, lingkungan hidup bukan hanya urusan teknis, tetapi bagian integral dari konstitusi yang mewajibkan negara hadir sebagai pelindung manusia sekaligus penjaga alam.
Peran Negara sebagai Penanggung Jawab
Sebagai pelaksana amanat konstitusi, negara melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus memainkan peran nyata. Regulasi yang kuat tanpa implementasi hanya akan menjadi kertas kosong. Oleh karena itu, negara berkewajiban membuat aturan yang jelas, menyediakan sumber daya untuk pengawasan, menjamin akses keadilan bagi warga terdampak, serta membuka ruang partisipasi publik.
Tanpa peran aktif negara, hak atas lingkungan sehat hanya akan menjadi retorika. Padahal, hak tersebut adalah hak dasar yang seharusnya tak bisa ditawar.
Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia
Walaupun fondasi hukum telah ada, praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan.
Pertama, lemahnya implementasi regulasi. UU PPLH memang memberi kerangka hukum bagi penegakan administratif, pidana, maupun perdata. Namun, dalam praktik, aparat pengawas sering kekurangan sumber daya, baik anggaran maupun keterampilan teknis. Akibatnya, banyak pelanggaran luput dari penindakan.
Kedua, rendahnya efek jera bagi korporasi. Sanksi administratif seperti denda sering dipandang sebagai biaya operasional biasa. Proses hukum pidana pun sulit ditempuh karena membutuhkan pembuktian ilmiah yang kompleks dan memakan waktu panjang.
Ketiga, adanya tumpang tindih regulasi dan konflik kepentingan. Regulasi yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah kerap menimbulkan interpretasi berlainan. Di sisi lain, kepentingan ekonomi sering mendominasi sehingga izin lingkungan dilemahkan demi percepatan investasi.
Kasus-Kasus Aktual
Kondisi di atas dapat dilihat dari sejumlah kasus nyata. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mencatat 74 perkara lingkungan selama semester pertama 2025, dengan 36 kasus dibawa ke pengadilan dan 15 sudah berkekuatan hukum tetap. Nilai pemulihan lingkungan yang berhasil dieksekusi mencapai Rp 86 miliar.
Namun, angka ini masih jauh dari memadai. Pada 2023 saja, tercatat 908 kasus kejahatan lingkungan di Indonesia. Di sektor air, lebih dari 11.000 desa mengalami pencemaran, terutama di Jawa. Penelitian di Tangerang menunjukkan kualitas air tanah di bantaran Sungai Cisadane menurun drastis, bahkan di beberapa titik melampaui ambang batas aman.
Polusi udara pun tak kalah mengkhawatirkan. Kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang, dan Bekasi berulang kali mencatat status unhealthy berdasarkan data AQI sepanjang 2024. Fakta ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup kuat menekan perilaku merusak lingkungan.
Urgensi Memperkuat Penegakan Hukum
Untuk mewujudkan keadilan ekologis, penguatan hukum mutlak dilakukan. Pertama, perlu adanya regulasi lex specialis yang lebih tegas dalam mengkriminalisasi kerusakan lingkungan besar-besaran, seperti pembakaran hutan atau pencemaran laut. Regulasi ini harus memperkuat kewenangan penyidik sekaligus memberikan kepastian hukum yang berbasis ilmu pengetahuan.
Kedua, Mahkamah Konstitusi dapat berperan penting dalam menafsirkan Pasal 28H UUD 1945. Melalui putusan pengujian norma, MK bisa mempertegas hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat.
Ketiga, akses keadilan bagi masyarakat harus diperluas. Mekanisme gugatan warga (citizen lawsuit) atau gugatan kelompok (class action) harus diperkuat agar masyarakat bisa menuntut haknya secara efektif. Pendampingan hukum dan dukungan pembiayaan litigasi menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi warga di hadapan korporasi besar.
Keempat, transparansi dan partisipasi publik harus dijamin. Proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), izin usaha, hingga rencana pemulihan pasca-kerusakan harus terbuka dan dapat diawasi publik.
Kelima, kapasitas aparat penegak hukum perlu ditingkatkan. Pengawasan berbasis teknologi seperti citra satelit, sensor kualitas udara dan air, serta laboratorium lingkungan dapat memperkuat validitas bukti. Tanpa pendekatan ilmiah, pembuktian hukum akan selalu melemahkan posisi negara di hadapan korporasi pelanggar.
Penutup
Lingkungan hidup bukan sekadar sumber daya yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Ia adalah ruang hidup manusia sekaligus warisan generasi yang wajib dijaga. Dengan menempatkan lingkungan sebagai hak konstitusional, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindunginya.
Jika negara abai, maka makna konstitusi akan hilang di mata rakyat. Karena itu, penguatan penegakan hukum adalah jalan untuk memastikan keadilan ekologis benar-benar hadir. Alam dan manusia harus hidup berdampingan dalam harmoni, bukan dalam relasi eksploitatif.
Keadilan ekologis tidak boleh berhenti sebagai gagasan. Ia harus menjadi kenyataan yang dirasakan setiap warga Indonesia dari kota besar hingga pelosok desa. Hanya dengan cara itu, kita bisa memastikan bahwa konstitusi tidak hanya hidup di atas kertas, melainkan juga berdenyut dalam kehidupan sehari-hari rakyatnya.
Referensi
- “Indonesia: Hampir 70 Persen Sumber Air Minum Rumah Tangga Tercemar Limbah Tinja.” UNICEF, 7 Februari 2022.
- “Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air.” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024.
- “Penegakan Hukum Lingkungan Kini Lebih Ilmiah dan Membumi: KLH/BPLH Ubah Cara Main.” Kementerian Lingkungan Hidup / BPLH, 24 Juni 2025.
- “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam RKUHP Alami Kemunduran.” Hukumonline, 18 Agustus 2022.
- Abd Jalil, Moh Fadhel, Muhamad Nabil Lamonsya, Muhammad Alisra Chivalry, Puja Maulana, Ikhwan Aulia Fatahillah. “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.” Jurnal Kritis Studi Hukum.
- “Penegakan Hukum Lemah, 6 Catatan Komnas HAM untuk Penanganan Karhutla.” Hukumonline, 4 Agustus 2025.
- Considine, Ellen M., dan Rachel C. Nethery. “A Spatiotemporal, Quasi-experimental Causal Inference Approach to Characterize the Effects of Global Plastic Waste Export and Burning on Air Quality Using Remotely Sensed Data.” arXiv (2025).
- Irawan, Dasapta Erwin, Deny Juanda Puradimaja, Defitri Yeni, Arno Adi Kuntoro, dan Miga Magenika Julian. “Decreasing Groundwater Quality at Cisadane Riverbanks: Groundwater-Surface Water Approach.” arXiv (2016).
- “Pencemaran Air di Indonesia.” DisLH Kabupaten Badung.
- “Optimalisasi Penegakan Hukum Lingkungan.” DetikNews, 9 Januari 2024.
- “Studi Kualitas Air, Status Mutu Air dan Beban Pencemaran Sungai Badung.” JWIKAL, 2024.
- “Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara di Indonesia.” ResearchGate.