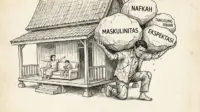Madura tidak hanya dikenal karena adat istiadat dan keberanian warganya, tetapi juga karena tradisi unik yang telah melekat dalam kehidupan masyarakatnya: kerapan sapi. Balapan sapi yang diadakan setiap musim kemarau ini bukan sekadar tontonan eksotis bagi wisatawan, melainkan manifestasi dari sistem berpikir yang khas dan mendalam.
Di balik gegap gempita lomba, tersimpan cara pandang masyarakat Madura yang patut dikaji melalui pendekatan filsafat ilmu khususnya penalaran, logika, dan kriteria kebenaran.
Kerapan sapi bukanlah sekadar hiburan musiman. Di tanah Madura, musim kemarau memang identik dengan lahan yang merekah dan daun-daun yang berguguran. Namun, bagi masyarakat setempat, ini juga menandai dimulainya ritual yang sakral sekaligus kompetitif.
Lapangan-lapangan terbuka disulap menjadi arena pacu, di mana dua ekor sapi dipacu sekencang mungkin oleh seorang joki kecil yang lihai dan pemberani. Semua tampak seperti hiburan rakyat, tetapi di baliknya terdapat logika yang dibangun dari generasi ke generasi.
Sering kali, filsafat ilmu dianggap sebagai wilayah akademik yang jauh dari kehidupan masyarakat adat. Namun, jika kita melihat lebih dekat, nilai-nilai seperti penalaran induktif, pragmatisme, dan koherensi logis justru hidup dan berkembang dalam tradisi seperti kerapan sapi.
Peternak dan pelatih sapi tidak sembarangan memilih pasangan sapi untuk diperlombakan. Pemilihan dilakukan berdasarkan pengalaman panjang dan pengamatan mendalam. Jenis sapi tertentu lebih cocok untuk lintasan berdebu, sementara jenis lainnya lebih tangguh di tanah basah. Pakan yang diberikan, waktu latihan, hingga pemilihan joki dan perhitungan cuaca pun dilakukan secara sistematis.
Praktik-praktik ini bukanlah takhayul, melainkan hasil dari logika alamiah dan pengetahuan lokal yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini adalah bentuk penalaran induktif dalam wujud paling nyata berangkat dari pengamatan terhadap pola dan hasil, hingga menjadi pengetahuan yang berakar kuat dalam kebudayaan.
Sementara itu, jika kita menguji tradisi kerapan sapi menggunakan kriteria kebenaran pragmatis, maka jelas terlihat bahwa ia membawa manfaat nyata: memperkuat identitas kolektif, menggerakkan roda perekonomian lokal, serta menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap warisan budaya mereka.
Jika diukur dengan teori koherensi, tradisi ini pun konsisten dengan sistem nilai dan struktur sosial masyarakat Madura. Dan melalui teori korespondensi, kita bisa melihat bagaimana kerapan sapi selaras dengan realitas kehidupan petani dan peternak Madura—cuaca, kondisi geografis, hingga ritme kerja mereka.
Kerapan sapi bukanlah produk dari irasionalitas atau kebiasaan semata. Ia adalah hasil dari cara berpikir yang sistematis, peka terhadap lingkungan, dan rasional dalam konteksnya sendiri. Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat adat pun memiliki sistem pengetahuan yang kompleks dan logis, meskipun tidak selalu dituangkan dalam bentuk akademik atau ilmiah seperti yang dikenal di dunia modern.
Apa yang ingin saya sampaikan sederhana: di balik debu yang beterbangan dan derap kaki sapi yang menghentak tanah, terdapat logika budaya yang hidup. Sudah saatnya kita tidak hanya memandang kerapan sapi sebagai tontonan atau potensi wisata, tetapi juga sebagai warisan berpikir yang berharga.
Di tengah zaman ketika algoritma digital semakin mendominasi cara kita mengambil keputusan, justru kita perlu kembali menengok bagaimana leluhur kita pernah berpikir secara cermat, dengan kepekaan yang tinggi, dan rasionalitas yang tidak kalah kuatnya.
Merawat kerapan sapi bukan hanya soal menjaga budaya visual dan performatif, tetapi juga merawat cara berpikir yang tumbuh dari tanah, alam, dan kehidupan masyarakat itu sendiri.