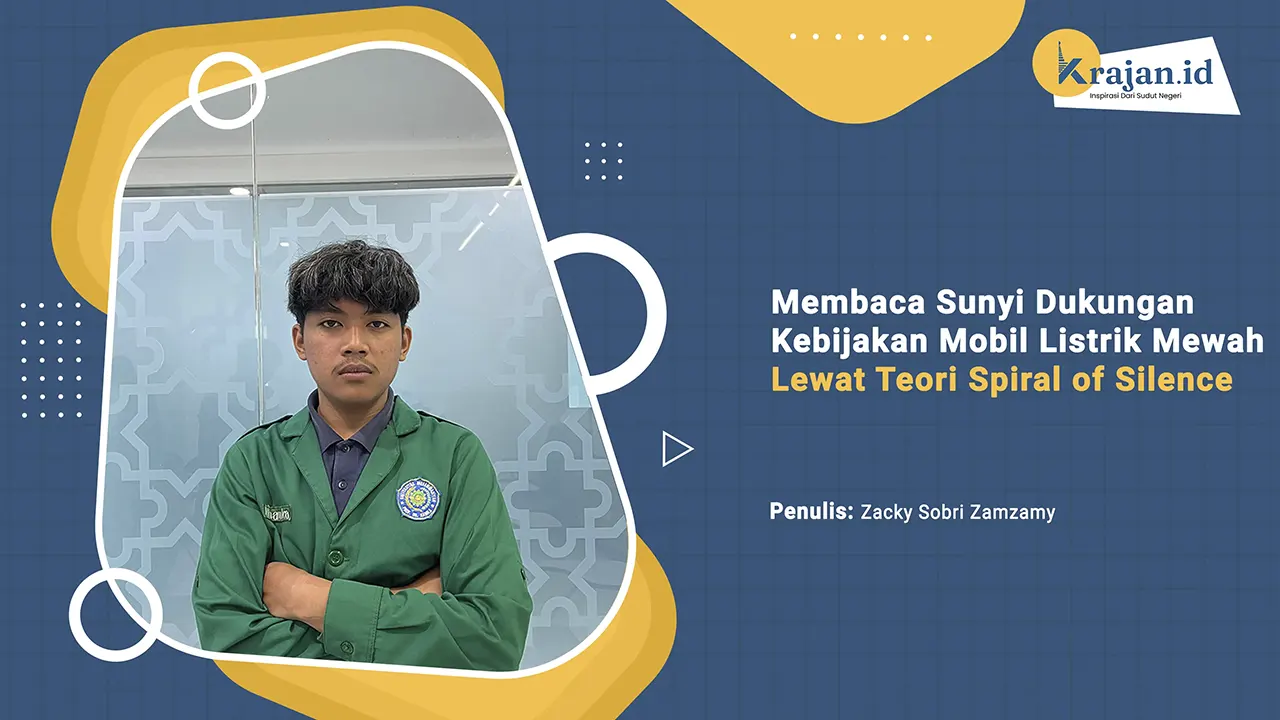Pemerintah Indonesia berencana menerapkan kebijakan pembebasan bea masuk untuk kendaraan listrik mulai awal tahun 2025. Kebijakan ini diperkirakan akan memberikan keuntungan bagi produsen mobil listrik mewah seperti Tesla dan Porsche.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi nasional untuk mendukung target emisi net-zero dan mempercepat transisi menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah meyakini bahwa insentif ini akan menarik investasi industri EV dan mempercepat peralihan masyarakat dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.
Namun, sejak diumumkan, kebijakan ini menuai respons beragam di ruang publik digital. Sebagian mendukung, menyebutnya sebagai terobosan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Sebagian lain mengkritik keras karena melihat kebijakan ini menguntungkan kelompok masyarakat atas, mengingat model kendaraan listrik yang mendapat pembebasan bea masuk umumnya adalah mobil-mobil berharga tinggi.
Kritik juga diarahkan pada kenyataan bahwa segmen masyarakat menengah ke bawah belum tersentuh dalam kebijakan ini. Sebagai contoh, kendaraan listrik berharga terjangkau atau moda transportasi publik berbasis listrik tidak mendapat prioritas yang sama.
Sentimen ketidakadilan sosial ini membuat kebijakan tersebut dilihat tidak inklusif dan justru memperlebar jurang ekonomi antar kelompok masyarakat.
Fenomena perdebatan ini menjadi semakin menarik ketika dikaji menggunakan perspektif teori spiral of silence yang dikemukakan Elisabeth Noelle-Neumann. Teori ini menyatakan bahwa seseorang cenderung menyembunyikan opininya ketika merasa pendapat tersebut bertentangan dengan opini publik dominan, demi menghindari risiko isolasi sosial. Dalam konteks ini, media sosial menjadi arena dinamis tempat teori ini hidup dan berkembang secara nyata.
Di media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, dinamika komunikasi publik tentang kebijakan ini memperlihatkan gejala spiral of silence yang signifikan. Pada awalnya, percakapan tampak seimbang. Banyak warganet yang menyambut baik kebijakan, terutama mereka yang melihat potensi pertumbuhan ekonomi hijau, investasi asing, serta perkembangan teknologi otomotif dalam negeri.
Namun, gelombang kritik segera membanjiri ruang digital. Ungkapan seperti “kebijakan untuk orang kaya”, “subsidi terselubung”, atau “rakyat hanya jadi penonton” mendominasi linimasa. Akun-akun berpengaruh dan influencer yang mengangkat sudut pandang kritis ini menerima ribuan like, komentar, dan retweet. Mereka menciptakan narasi dominan yang menyudutkan pendapat yang pro kebijakan.
Di sinilah spiral of silence bekerja. Pendapat yang mendukung kebijakan mulai jarang terdengar, bukan karena tidak ada, melainkan karena pengusungnya enggan menyuarakan argumennya. Ketakutan akan dicap sebagai ‘antek kapitalis’ atau ‘tidak peka pada ketimpangan sosial’ membuat warganet pendukung lebih memilih diam. Mereka menghindari perdebatan karena takut mengalami perundungan digital atau dikeluarkan dari lingkaran sosial mereka.
Ketakutan akan isolasi ini menjadi elemen kunci dalam spiral of silence. Persepsi bahwa opini mayoritas adalah yang paling banyak dibicarakan membuat banyak orang menyembunyikan pandangan berbeda.
Padahal, opini dominan yang terlihat belum tentu merepresentasikan pandangan mayoritas yang sebenarnya. Dalam kasus ini, pendukung kebijakan masih ada, namun tekanan sosial membuat mereka pasif di ruang diskusi publik.
Media sosial, dengan fitur seperti retweet, like, dan share, mempercepat terbentuknya persepsi mayoritas semu. Kuantitas interaksi menjadi indikator kekuatan opini, bukan kualitas argumen. Dengan begitu, narasi kontra kebijakan yang viral menciptakan ilusi bahwa seluruh masyarakat menolaknya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi tempat berbagi informasi, tetapi juga tempat pembentukan opini publik secara real time. Sayangnya, kecepatan ini tidak selalu diikuti oleh kedalaman analisis. Banyak opini dibentuk oleh emosi sesaat, bukan refleksi rasional. Di tengah keterbukaan ruang digital, muncul pula kecenderungan masyarakat untuk cepat menghakimi.
Sebagian pengguna media sosial yang awalnya mendukung kebijakan, perlahan menarik diri dari percakapan setelah menyaksikan hujatan yang dialami oleh mereka yang pro. Ketika satu suara diserang secara terbuka, maka kelompok pendukung lainnya belajar untuk tetap diam demi menjaga stabilitas relasi sosial mereka.
Dalam situasi semacam ini, diskursus publik menjadi timpang. Perdebatan yang sehat dan beragam tereduksi menjadi monolog kelompok dominan. Ruang dialog hilang karena tekanan untuk konformitas meningkat. Akibatnya, kebijakan publik tidak mendapat masukan yang seimbang. Pemerintah pun bisa kehilangan perspektif dari kelompok pendukung karena mereka tidak terlihat bersuara.
Menariknya, teori spiral of silence yang lahir pada 1974, jauh sebelum era digital, justru menjadi semakin relevan saat ini. Media sosial memperkuat kondisi-kondisi yang digambarkan dalam teori ini: percepatan pembentukan opini dominan, rasa takut akan isolasi sosial, dan pengaruh kuat persepsi mayoritas terhadap keberanian individu menyampaikan pandangannya.
Kritik terhadap kebijakan mobil listrik mewah ini memang sah dan perlu, terutama jika diarahkan pada upaya agar kebijakan menjadi lebih adil. Namun, ruang publik juga harus memastikan bahwa semua suara mendapat tempat. Dukungan terhadap kebijakan pun layak disuarakan tanpa takut dikucilkan.
Literasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Masyarakat harus dibekali kemampuan membedakan opini populer dengan kebenaran rasional. Kita perlu membangun budaya berdiskusi yang sehat dan menghargai perbedaan pendapat. Dalam masyarakat yang demokratis, keberagaman opini adalah kekayaan, bukan ancaman.
Spiral of silence menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan kebebasan berbicara, tetapi juga keberanian untuk berbeda. Dalam kasus kebijakan pembebasan bea masuk mobil listrik mewah, kita belajar bahwa suara yang sunyi bukan berarti tidak ada. Ia hanya terkubur dalam ketakutan, menunggu ruang aman untuk muncul kembali.
Sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi, saya melihat fenomena ini sebagai refleksi bahwa literasi media dan komunikasi publik harus menjadi bagian dari pendidikan masyarakat. Kita harus mendidik generasi digital agar tidak hanya mampu beropini, tetapi juga mampu menciptakan ruang dialog yang inklusif dan adil.