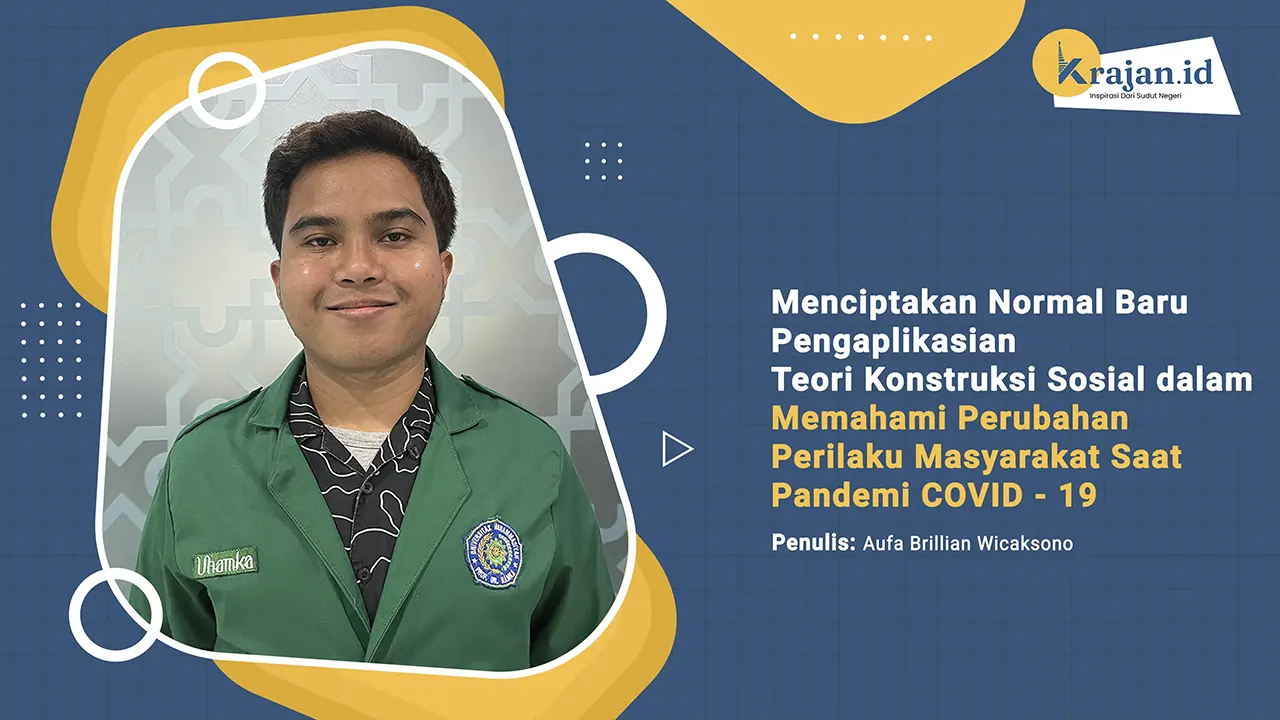Pandemi COVID-19 tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga menjadi katalis lahirnya normal baru yang dibentuk melalui proses konstruksi sosial.
Pandemi COVID-19 memaksa masyarakat untuk beradaptasi secara drastis. Perubahan yang semula terasa asing, seperti mengenakan masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan secara berkala, kini telah menjadi kebiasaan sehari-hari. Fenomena ini bisa dijelaskan melalui teori konstruksi sosial, yaitu bagaimana realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivisasi, dan internalisasi yang dijalani bersama oleh masyarakat.
Kondisi krisis mendorong masyarakat menciptakan makna baru terhadap tindakan yang sebelumnya dianggap tidak lazim. Interaksi sosial menjadi lebih berhati-hati. Saling sapa kini cukup dilakukan dari kejauhan, bahkan komunikasi virtual menjadi pilihan utama. Walau sempat menimbulkan disorientasi, kebiasaan-kebiasaan baru ini perlahan menjadi bagian dari tatanan hidup yang dianggap “normal”.
Namun, tak semua individu menerima perubahan ini dengan mudah. Ada sebagian masyarakat yang tetap bersikap acuh terhadap protokol kesehatan. Dalam kerangka teori konstruksi sosial, sikap tersebut memperlihatkan ketimpangan dalam proses internalisasi nilai-nilai baru.
Ketika individu tidak mampu memahami bahwa perilaku baru merupakan bentuk tanggung jawab kolektif, maka realitas sosial yang hendak dibentuk menjadi lemah dan mudah goyah.
Penerapan “normal baru” pun bukan tanpa hambatan. Banyak masyarakat yang justru mengalami penurunan aktivitas fisik karena keterbatasan ruang gerak. Di sisi lain, virus yang menyebar dengan cepat mengharuskan masyarakat tetap waspada, termasuk dengan menghindari kerumunan, menjaga kebersihan, dan menjaga daya tahan tubuh melalui asupan gizi seimbang.
Media massa berperan besar dalam membentuk opini publik selama pandemi. Media tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga menjadi agen penting dalam menyosialisasikan protokol kesehatan dan membangun kesadaran kolektif.
Namun, tak jarang media juga menampilkan berita dengan nada sensasional yang justru menimbulkan ketakutan. Di sinilah publik perlu lebih kritis dalam menafsirkan informasi mana yang faktual, mana yang emosional.
Dalam kerangka sosial budaya Indonesia yang kuat dengan nilai gotong royong, menjaga jarak sosial menjadi tantangan tersendiri. Jaga jarak secara fisik kadang dipahami sebagai menjauh secara sosial.
Padahal, manusia sebagai makhluk sosial masih tetap bisa membangun kebersamaan melalui interaksi digital. Aktivitas seperti work from home, kuliah daring, seminar virtual, dan diskusi online menjadi bukti bahwa interaksi sosial tetap berlangsung meskipun dalam format baru.
Pemerintah sendiri telah berupaya keras menanggulangi pandemi melalui kebijakan PSBB, PPKM, serta kampanye vaksinasi nasional. Upaya ini dilengkapi dengan edukasi publik tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dari sini tampak bahwa pemerintah tidak hanya berupaya mengontrol situasi secara fisik, tetapi juga mencoba membentuk realitas sosial baru yang lebih sehat dan berdaya tahan.
Kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan memang terus dibangun. Namun, perubahan besar semacam ini tidak cukup hanya dari atas (top-down), tetapi juga butuh partisipasi aktif dari masyarakat. Proses sosialisasi, baik melalui media, sekolah, komunitas, maupun figur publik, menjadi saluran penting agar norma-norma baru bisa diterima dan dijalankan dengan sukarela.
Di tengah krisis, lahir pula berbagai bentuk inovasi sosial. Masyarakat menciptakan solusi adaptif, seperti mengembangkan sistem kerja jarak jauh, menciptakan platform edukasi daring, hingga membentuk komunitas relawan. Gotong royong muncul kembali, baik dalam bentuk distribusi bantuan sosial, penyediaan masker gratis, hingga penyediaan layanan kesehatan berbasis komunitas.
Lebih jauh, pandemi memunculkan identitas sosial baru: dari “aku” menjadi “kita”. Perubahan ini tampak dari semakin banyaknya praktik sosial yang menekankan solidaritas, saling peduli, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, tradisi berjabat tangan berganti dengan anggukan kepala, atau kegiatan ibadah dilakukan secara daring tanpa mengurangi kekhusyukan.
Masyarakat juga menemukan sosok-sosok pahlawan baru di tengah krisis. Para tenaga kesehatan, relawan, guru daring, hingga para tetangga yang membantu sesama menjadi inspirasi kolektif. Kisah-kisah mereka yang tersebar di media sosial dan media arus utama tidak hanya menjadi hiburan, melainkan menjadi alat pendidikan moral yang memperkuat nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial.
Pengakuan terhadap para pahlawan ini juga memperkuat norma timbal balik dalam masyarakat. Ketika tindakan positif diberi penghargaan sosial, maka orang lain akan terdorong untuk berbuat serupa. Inilah awal dari terbentuknya siklus sosial positif, di mana setiap individu melihat kontribusinya sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif. Norma baru yang menempatkan kepedulian sosial sebagai nilai utama perlahan tertanam dalam kesadaran masyarakat.
Di balik semua itu, perubahan yang kita saksikan selama pandemi bukan sekadar hasil dari kebijakan pemerintah atau dorongan media. Perubahan ini adalah hasil dari konstruksi sosial yang dibentuk secara kolektif di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang aktif dalam membentuk kenyataan baru. Dengan kata lain, masyarakat sendiri ikut menciptakan makna baru dari krisis ini dan bersama-sama menenun struktur sosial yang lebih adaptif dan resilien.
Konstruksi sosial atas “normal baru” ini menjadi bukti nyata bahwa perubahan perilaku bukan hanya didorong oleh ketakutan, tetapi juga oleh kesadaran. Inilah yang menjadi kekuatan utama dalam menghadapi krisis: solidaritas, kreativitas, dan ketangguhan sosial. Maka, pandemi COVID-19, meskipun menyisakan luka, juga meninggalkan warisan sosial berupa norma-norma baru yang lebih empatik, sehat, dan kolaboratif.
Pandemi COVID-19 merupakan titik balik dalam sejarah sosial kontemporer yang membentuk kembali cara masyarakat memahami dan menjalani kehidupan. Teori konstruksi sosial memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana perubahan perilaku baik individu maupun kolektif dapat muncul dan bertahan.
Transformasi ini bukan semata-mata hasil kebijakan atau instruksi teknokratik, tetapi lahir dari partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan menafsirkan ulang makna hidup bersama. Inilah cikal bakal tatanan sosial baru yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlangsungan hidup yang sehat dan bermakna.