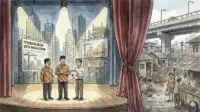Ketika dunia bergerak dengan kecepatan yang nyaris tak terbendung, masyarakat Baduy Dalam tetap teguh menjaga nilai-nilai warisan leluhurnya. Hidup tanpa listrik, tanpa kendaraan bermotor, dan tanpa akses internet bukanlah pilihan karena keterbatasan, melainkan karena keyakinan bahwa kesederhanaan adalah bentuk kehidupan yang paling selaras dengan alam.
Segala tatanan ini diatur oleh Pikukuh Karuhun, sebuah pedoman adat yang menjadi dasar hidup masyarakat Baduy.
Namun ketenangan itu sempat terganggu. Pada tahun 2021, enam unit sepeda motor ditemukan memasuki kawasan Baduy Dalam, wilayah yang secara adat seharusnya steril dari segala bentuk teknologi bermesin. Peristiwa ini bukanlah pelanggaran biasa. Bagi masyarakat Baduy, ini adalah bentuk pencemaran terhadap ruang suci mereka.
Kejadian tersebut terungkap saat warga melakukan patroli rutin. Enam motor ditemukan dan empat di antaranya langsung dibakar di tempat. Aksi ini terekam dan tersebar di media sosial, menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat luas. Ada yang mengagumi ketegasan masyarakat adat dalam mempertahankan nilai-nilainya, namun ada pula yang menilai tindakan tersebut terlalu ekstrem.
Namun bagi masyarakat Baduy, tindakan itu bukanlah bentuk amarah atau balas dendam. Pembakaran tersebut adalah simbol pembersihan, bentuk nyata dari upaya menjaga kesucian wilayah adat mereka.
Dalam pandangan masyarakat adat, segala sesuatu yang mengganggu harmoni harus disingkirkan. Proses ini dilakukan berdasarkan kesepahaman kolektif yang ditanamkan sejak kecil melalui pendidikan adat, cerita turun-temurun, dan teladan dari para tokoh adat.
Meski tidak tertulis dalam hukum negara, aturan adat Baduy memiliki kekuatan tersendiri. Dalam Pikukuh Karuhun, jelas tercantum larangan menggunakan listrik, kendaraan bermotor, dan praktik perdagangan tertentu. Ini bukan karena mereka menolak kemajuan, melainkan karena mereka ingin menjaga hubungan harmonis dengan alam, sesama, dan para leluhur.
Jika terjadi pelanggaran, penyelesaiannya bukan melalui kepolisian atau pengadilan, tetapi oleh para tokoh adat seperti Puun dan Jaro. Karena bagi mereka, adat adalah jalan hidup, bukan sekadar kumpulan tradisi. Tindakan seperti membakar motor menjadi bentuk nyata dari penegakan hukum adat yang menekankan pada pemulihan, bukan penghukuman.
Pendekatan yang digunakan masyarakat Baduy sejalan dengan konsep keadilan restoratif, di mana yang utama bukanlah mencari siapa yang salah dan menghukumnya, melainkan bagaimana harmoni yang terganggu dapat dipulihkan.
Pemilik kendaraan tidak dikucilkan, mereka tetap diterima kembali setelah menjalani proses adat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang humanis dan berbasis komunitas masih sangat relevan diterapkan.
Beberapa teori hukum modern memberikan penjelasan atas kekuatan hukum adat seperti di Baduy. Eugen Ehrlich dengan Living Law menyatakan bahwa hukum yang benar-benar hidup adalah hukum yang dijalani dalam keseharian masyarakat, bukan sekadar teks dalam dokumen resmi. B. Ter Haar memandang hukum adat sebagai bagian integral dari kehidupan sosial, di mana pelanggaran individu berdampak pada keseluruhan komunitas.
Sementara John Braithwaite melalui konsep Reintegrative Shaming menekankan bahwa rasa malu yang dibangun secara kolektif bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke dalam komunitas, bukan mengucilkannya.
Di sisi lain, teori legal pluralism menjelaskan bahwa dalam satu negara bisa hidup beberapa sistem hukum sekaligus—negara, agama, dan adat—dan semuanya memiliki legitimasi tersendiri.
Hukum adat seperti di Baduy juga mendapatkan pengakuan secara formal. Konstitusi Indonesia dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Di tingkat internasional, Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) juga menegaskan bahwa masyarakat adat berhak mengatur hidupnya sendiri, termasuk melindungi dan melestarikan budayanya.
Namun, tantangan bagi masyarakat Baduy tidak berhenti sampai di situ. Arus modernisasi kini semakin terasa, terutama di wilayah Baduy Luar. Teknologi, wisata, dan media sosial mulai merambah, membawa pengaruh yang tidak dapat dihindari.
Meski demikian, Baduy Dalam tetap konsisten menjaga jarak. Mereka bahkan pernah meminta agar sinyal internet di sekitar wilayah mereka dimatikan. Ini bukan bentuk kebencian terhadap teknologi, melainkan upaya menjaga agar generasi muda tetap tumbuh dengan nilai-nilai adat yang telah diwariskan sejak lama.
Pertanyaannya kemudian adalah: siapa yang seharusnya menyesuaikan? Dalam kisah masyarakat Baduy, kita melihat bahwa kemajuan tidak harus berarti meninggalkan jati diri. Mereka tidak menolak masa depan, mereka hanya memilih untuk menyambutnya dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai mereka sendiri. Tradisi bukanlah musuh perubahan, justru bisa menjadi pondasi kuat untuk menghadapi perubahan itu sendiri.
Cerita masyarakat Baduy mengajarkan kita bahwa menjaga tradisi di tengah arus modernisasi bukan berarti anti kemajuan. Sebaliknya, dari keteguhan mereka, kita belajar bahwa melestarikan nilai-nilai lokal adalah salah satu cara paling bijak untuk membangun masa depan yang berkelanjutan dan bermartabat.