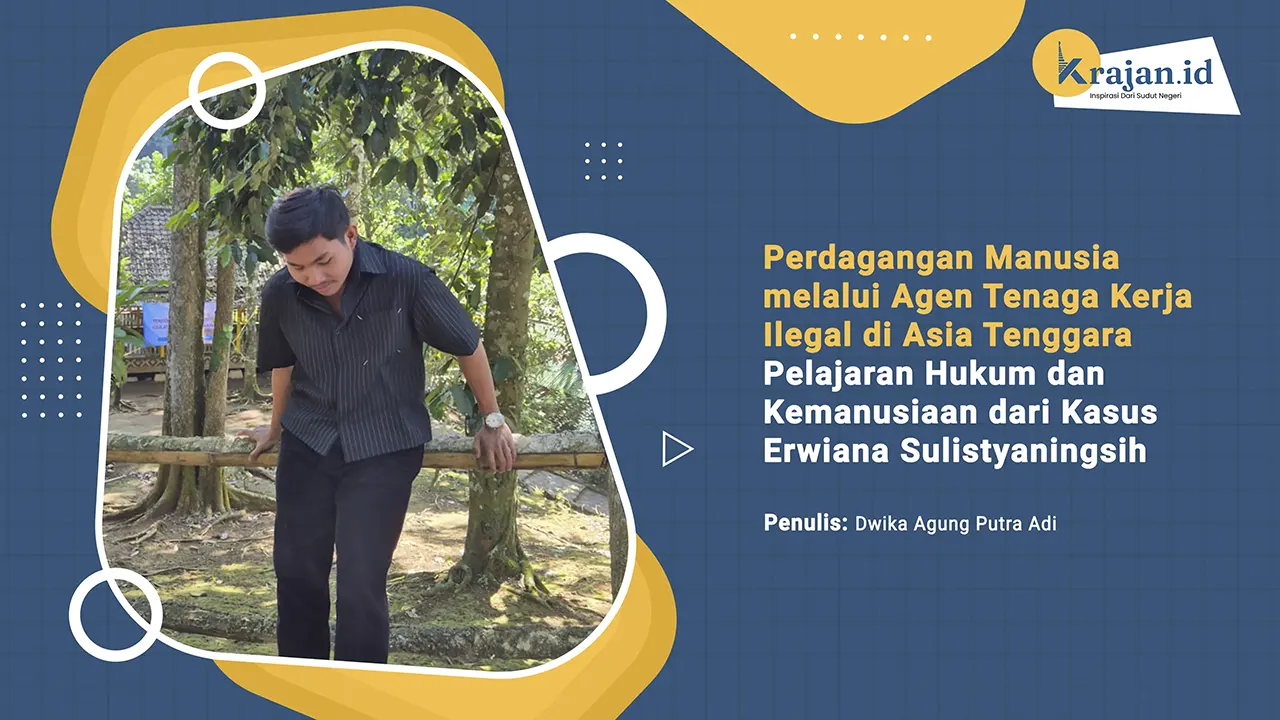Perdagangan manusia masih menjadi luka terbuka dalam tata kelola migrasi tenaga kerja di Asia Tenggara. Praktik ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan kemiskinan struktural, lemahnya pengawasan negara, serta keberadaan jaringan agen tenaga kerja ilegal yang memanfaatkan kerentanan sosial ekonomi masyarakat.
Salah satu potret paling telanjang dari praktik tersebut tercermin dalam kasus Erwiana Sulistyaningsih, pekerja migran Indonesia yang mengalami penyiksaan berat di Hong Kong. Kasus ini bukan sekadar kisah kekerasan individual, melainkan cermin kegagalan sistemik dalam melindungi martabat manusia.
Erwiana Sulistyaningsih lahir pada 8 Juni 1991 di Karanganyar, sebuah desa kecil di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ia tumbuh dalam keluarga petani kecil dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Ayahnya menggantungkan hidup dari lahan sempit, sementara ibunya bekerja sebagai buruh tani.
Sebagai anak ketiga dari lima bersaudara, Erwiana sejak dini terbiasa membantu orang tuanya di sawah. Keterbatasan ekonomi membuat pendidikannya terhenti pada jenjang sekolah menengah pertama. Realitas ini bukan pengecualian, melainkan gambaran umum jutaan warga desa di Indonesia yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan antargenerasi.
Memasuki awal dekade 2010-an, tekanan ekonomi di perdesaan semakin nyata. Lapangan kerja terbatas, upah sektor pertanian rendah, dan mobilitas sosial nyaris buntu. Dalam situasi seperti ini, migrasi tenaga kerja ke luar negeri kerap dipersepsikan sebagai jalan keluar rasional.
Asia Tenggara menjadi kawasan dengan arus migrasi pekerja domestik terbesar di dunia. Jutaan warga Indonesia, Filipina, dan negara lain berangkat ke Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Kisah sukses para pekerja migran yang mampu mengirim uang ke kampung halaman menciptakan ilusi keberhasilan yang sering kali menutupi risiko besar di baliknya.
Erwiana, yang saat itu berusia sekitar 21 tahun, terpengaruh oleh cerita-cerita tersebut. Ia berharap dapat membantu perekonomian keluarga, membiayai pendidikan adik-adiknya, dan merawat orang tuanya yang sakit. Niat ini sepenuhnya rasional dan manusiawi. Namun, dalam konteks migrasi tenaga kerja yang minim literasi hukum dan perlindungan, niat baik kerap menjadi pintu masuk eksploitasi.
Pada 2013, Erwiana mulai menghubungi agen tenaga kerja di Surabaya. Di titik inilah mekanisme perdagangan manusia bekerja secara sistematis. Agen tenaga kerja ilegal, yang beroperasi di luar pengawasan negara, menawarkan janji gaji tinggi, pekerjaan layak, dan kontrak resmi.
Erwiana diminta membayar biaya administrasi yang besar, berkisar antara lima hingga sepuluh juta rupiah. Agen menjanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Hong Kong dengan gaji minimal empat ribu dolar Hong Kong per bulan. Janji tersebut disampaikan tanpa transparansi, tanpa dokumen resmi, dan tanpa jaminan perlindungan hukum.
Agen yang merekrut Erwiana tidak terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka merupakan bagian dari jaringan lintas negara yang memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan. Dokumen perjalanan dimanipulasi, prosedur keberangkatan dipercepat secara tidak sah, dan calon pekerja ditempatkan sebagai komoditas. Pola ini merupakan ciri khas perdagangan manusia modern, di mana eksploitasi dibungkus dengan narasi kesempatan kerja.
Setelah membayar biaya perekrutan, Erwiana menjalani pelatihan singkat. Materinya terbatas pada pengenalan dasar bahasa Kanton dan pekerjaan rumah tangga. Pelatihan ini lebih bersifat formalitas agar calon pekerja terlihat layak di mata majikan, bukan untuk membekali mereka dengan pemahaman hak dan perlindungan hukum.
Pada Mei 2013, Erwiana diberangkatkan ke Hong Kong melalui Bandara Soekarno-Hatta. Proses ini difasilitasi oleh agen dengan visa kerja sementara yang prosedurnya tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada korban.
Di Hong Kong, Erwiana dipertemukan dengan majikannya, Law Wan-tung, seorang perempuan yang tinggal di kawasan Tuen Mun. Sejak Juni 2013, Erwiana mulai bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Pada awalnya, situasi tampak normal.
Ia menjalankan tugas membersihkan rumah, merawat anak, dan pekerjaan domestik lainnya. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama. Dalam hitungan minggu, pekerjaan tersebut berubah menjadi ruang penyiksaan.
Law Wan-tung mulai melakukan kekerasan fisik dan mental secara sistematis. Erwiana dipaksa bekerja lebih dari 18 jam sehari tanpa waktu istirahat yang layak. Ia kerap tidak diberi makan, dipukul, disiram air panas, dan dipaksa tetap bekerja meski sakit.
Paspor dan dokumen pribadinya disita, sehingga ia kehilangan kebebasan bergerak. Ia dilarang keluar rumah dan diisolasi dari dunia luar. Upah yang dijanjikan tidak pernah dibayarkan secara utuh. Kondisi ini menempatkan Erwiana dalam situasi kerja paksa yang memenuhi seluruh karakteristik perbudakan modern.
Jika ditelaah dari perspektif hukum pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kasus Erwiana secara terang memenuhi seluruh unsur tindak pidana perdagangan manusia.
Unsur pertama adalah perbuatan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang. Perekrutan Erwiana oleh agen ilegal di Surabaya, penampungannya sebelum keberangkatan, hingga pengirimannya ke Hong Kong merupakan rangkaian perbuatan yang terorganisasi. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan pemindahan lintas negara.
Unsur perbuatan ini tidak berdiri sendiri. Agen menerima sejumlah uang dari korban sebagai biaya penempatan, memperlakukan korban sebagai objek transaksi, dan menyerahkannya kepada pihak majikan di negara tujuan. Praktik ini mencerminkan pola perdagangan manusia, bukan sekadar penempatan kerja ilegal. Ketiadaan pengawasan negara memperparah posisi rentan korban.
Unsur kedua adalah cara yang digunakan pelaku. Dalam kasus ini, cara tersebut berupa penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, serta manipulasi dokumen. Agen memanfaatkan kemiskinan dan keterbatasan pendidikan Erwiana.
Janji gaji tinggi dan perlindungan hukum disampaikan tanpa dasar. Informasi yang diberikan tidak lengkap dan menyesatkan. Dokumen perjalanan diproses secara tidak transparan, melanggar prosedur resmi. Setelah tiba di Hong Kong, majikan menyita paspor dan menggunakan ancaman serta kekerasan untuk memaksa korban patuh. Semua tindakan ini memenuhi unsur cara sebagaimana diatur dalam UU TPPO.
Unsur ketiga adalah tujuan eksploitasi. Inilah inti dari tindak pidana perdagangan manusia. Eksploitasi yang dialami Erwiana mencakup kerja paksa, kekerasan fisik, penyiksaan mental, dan eksploitasi ekonomi. Ia dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi, kehilangan kebebasan, dan tidak menerima hak dasar sebagai pekerja.
Penguasaan penuh atas tubuh, waktu, dan identitas korban menunjukkan bahwa tujuan sejak awal adalah eksploitasi, bukan hubungan kerja yang sah. Dengan demikian, seluruh unsur TPPO terpenuhi secara utuh dan tidak terbantahkan.
Penegakan hukum dalam kasus ini berlangsung di dua yurisdiksi. Di Hong Kong, aparat penegak hukum menangkap dan mengadili Law Wan-tung setelah kasus ini mencuat ke publik internasional. Sistem hukum Hong Kong mengklasifikasikan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai tindak pidana serius. Majikan dijerat dengan pasal penganiayaan, penyiksaan, dan pelanggaran ketenagakerjaan. Putusan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dan kewajiban ganti rugi kepada korban.
Kasus ini menunjukkan bahwa keberanian korban untuk melapor sangat menentukan. Peran media, organisasi masyarakat sipil, dan dukungan pemerintah Indonesia turut memperkuat proses penegakan hukum.
Tekanan publik internasional membuat proses peradilan berjalan lebih cepat dan transparan. Meski demikian, tidak semua korban memiliki kesempatan dan dukungan serupa. Banyak kasus perdagangan manusia berhenti di balik tembok rumah majikan tanpa pernah tersentuh hukum.
Di sisi lain, penegakan hukum juga harus dilihat dari perspektif perlindungan korban. Dalam kasus Erwiana, perlindungan dilakukan melalui pemulihan medis, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, BP2MI, dan KBRI Hong Kong berperan dalam memberikan dukungan administratif dan hukum. Perlindungan ini penting untuk mencegah intimidasi dan memastikan korban dapat memberikan kesaksian tanpa tekanan. Dalam konteks TPPO, perlindungan korban bukan sekadar aspek kemanusiaan, tetapi bagian integral dari penegakan hukum pidana.
Hubungan hukum antara pekerja migran dan agen tenaga kerja seharusnya bersifat kontraktual dan sah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur kewajiban agen penempatan untuk memberikan informasi yang benar, memproses dokumen secara legal, serta melindungi pekerja sebelum, selama, dan setelah bekerja.
Namun, dalam kasus Erwiana, hubungan hukum ini tidak pernah ada. Agen yang merekrutnya ilegal dan beroperasi di luar sistem hukum. Ketiadaan kontrak resmi dan perlindungan mengubah hubungan tersebut menjadi relasi eksploitatif yang berpotensi pidana.
Dari perspektif hukum perdata, majikan memiliki tanggung jawab besar atas kerugian yang dialami korban. Tindakan penyiksaan, penahanan dokumen, kerja paksa, dan tidak dibayarkannya upah merupakan perbuatan melawan hukum.
Majikan wajib mengganti kerugian materiil berupa upah yang tidak dibayar dan biaya pengobatan, serta kerugian imateriil berupa penderitaan psikologis dan trauma. Dalam konteks TPPO, kewajiban ini diperkuat dengan ketentuan restitusi yang mencakup seluruh kerugian fisik, mental, dan ekonomi korban.
Kasus Erwiana juga menegaskan peran negara dalam melindungi warga negara di luar negeri. Perlindungan ini bukan pilihan, melainkan kewajiban konstitusional. Negara harus hadir sejak tahap pencegahan, penempatan, hingga pemulihan korban.
Pengawasan terhadap agen tenaga kerja harus diperketat, edukasi calon pekerja migran ditingkatkan, dan kerja sama bilateral dengan negara tujuan diperkuat. Tanpa pembenahan sistemik, kasus serupa akan terus berulang dengan korban yang berbeda.
Pengalaman Erwiana mengajarkan bahwa perdagangan manusia bukan kejahatan yang terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari kemiskinan struktural, minimnya literasi hukum, dan lemahnya tata kelola migrasi tenaga kerja.
Selama negara gagal membangun sistem penempatan yang transparan dan mudah diakses hingga tingkat desa, ruang bagi agen ilegal akan selalu terbuka. Perlindungan pekerja migran tidak cukup berhenti pada regulasi di atas kertas. Ia menuntut kehadiran negara yang nyata, konsisten, dan berpihak pada martabat manusia.