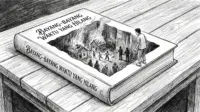Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang siswa terhadap hubungan manusia dengan masyarakat dan lingkungan alamnya.
IPS bukan hanya tentang memahami konsep ekonomi, sejarah, atau geografi, melainkan juga tentang bagaimana peserta didik mampu menafsirkan keterkaitan antara tindakan manusia dan dampaknya terhadap keberlanjutan bumi.
Di tengah meningkatnya tantangan global seperti perubahan iklim, deforestasi, hingga krisis air bersih, pembelajaran IPS seharusnya tidak berhenti pada penyampaian fakta, tetapi harus menjadi ruang pembentukan kesadaran kritis dan solusi nyata bagi keberlanjutan lingkungan.
Data dari PISA 2018 yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa literasi lingkungan siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata internasional. Artinya, banyak siswa yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai isu-isu ekologis dan belum mampu menerapkan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari.
Kondisi ini menegaskan pentingnya reformasi metode pembelajaran, salah satunya melalui pendekatan Project-Based Learning (PBL) atau pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan ini mendorong siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung, berkolaborasi dengan teman, dan menghasilkan karya konkret yang berdampak pada lingkungan sekitarnya.
Konsep PBL sendiri telah dikenal sejak awal abad ke-20, diperkenalkan oleh John Dewey, tokoh pendidikan progresif yang menekankan pentingnya pengalaman autentik dalam proses belajar. Dalam konteks Indonesia, Kurikulum Merdeka yang diterapkan oleh Kemendikbudristek sejak tahun 2022 telah mengintegrasikan pendekatan ini, terutama pada mata pelajaran IPS. PBL dianggap sejalan dengan visi Profil Pelajar Pancasila yang menumbuhkan karakter bernalar kritis, kreatif, dan berwawasan global.
Dari sisi teori, PBL berakar pada pendekatan konstruktivisme, yaitu pandangan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi aktif dengan dunia nyata. Menurut Krajcik dan Blumenfeld (2006), PBL memiliki lima elemen utama: adanya pertanyaan penggerak, riset berbasis bukti, kerja sama tim, pembuatan produk nyata, serta refleksi kritis.
Dalam pembelajaran IPS di SMP, kelima elemen ini dapat dirancang agar sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum Merdeka, misalnya KD 3.2 kelas 8 tentang interaksi manusia dan lingkungan serta dampaknya terhadap keberlanjutan.
Tujuan pembelajaran pun mencakup tiga ranah: kognitif (pemahaman konsep ekosistem), afektif (empati terhadap masyarakat terdampak bencana), dan psikomotorik (kemampuan membuat solusi praktis seperti program daur ulang).
Tahapan perencanaan proyek dimulai dari analisis kebutuhan siswa. Guru dapat melakukan survei sederhana untuk memetakan masalah lingkungan sekitar, seperti penumpukan sampah plastik di sungai atau erosi tanah di lahan pertanian. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa usia 12–15 tahun yang menurut Jean Piaget berada pada tahap berpikir operasional formal, yakni mampu berpikir abstrak tetapi masih membutuhkan bimbingan konkret. Di sekolah inklusif, prinsip diferensiasi juga penting agar siswa berkebutuhan khusus tetap dapat berpartisipasi aktif.
Sebuah penelitian oleh Bell (2010) menunjukkan bahwa tanpa perencanaan dan evaluasi yang jelas, hampir 40% implementasi PBL di sekolah menengah berpotensi gagal. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan kerangka kerja yang sistematis seperti siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act).
Pada tahap Plan, guru menyusun rancangan proyek selama empat hingga enam pertemuan dengan alokasi waktu sesuai Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018. Pertanyaan penggerak harus bersifat menantang dan kontekstual, misalnya: “Bagaimana aktivitas manusia di kota besar memperburuk kerusakan lingkungan, dan apa kontribusi kita untuk memperbaikinya?”
Pada tahap Do, siswa bekerja dalam kelompok kecil beranggotakan empat hingga lima orang. Mereka melakukan observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat, hingga membuat produk kreatif seperti video kampanye atau prototipe tempat sampah daur ulang.
Dalam proses ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan scaffolding sesuai teori Vygotsky tentang Zone of Proximal Development. Penggunaan teknologi seperti Google Earth atau aplikasi Canva dapat membantu, namun guru juga harus memperhatikan keterbatasan fasilitas di daerah terpencil.
Tahap Check berfokus pada evaluasi hasil proyek. Guru dapat menilai dari berbagai aspek, seperti kerja sama tim (30%), kualitas produk (40%), dan refleksi afektif (30%). Refleksi ini bisa dilakukan melalui jurnal belajar atau survei sederhana seperti, “Apakah proyek ini mengubah pandangan Anda terhadap tanggung jawab menjaga lingkungan?” Sedangkan pada tahap Act, guru bersama siswa melakukan perbaikan dan pengayaan proyek berdasarkan umpan balik yang diterima.
Sebagai contoh penerapan nyata, proyek kelas 8 bertema “Keberlanjutan Sumber Daya Alam: Kasus Deforestasi di Kalimantan” dapat dijalankan. Siswa diminta meneliti bagaimana ekspansi perkebunan sawit memengaruhi masyarakat adat Dayak dan ekosistem hutan tropis.
Mereka melakukan riset daring menggunakan data dari KLHK dan wawancara virtual dengan aktivis lingkungan WALHI. Hasil proyek berupa video kampanye bertajuk “Hutan untuk Masa Depan” kemudian diunggah di akun media sosial sekolah.
Evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman konsep keberlanjutan sebesar 25% dari pre-test ke post-test, dan sekitar 80% siswa menyatakan ingin mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dari sini terlihat bahwa PBL mampu menjembatani teori IPS dengan realitas sosial, sekaligus menumbuhkan nilai gotong royong, kepedulian, dan tanggung jawab.
Namun, penerapan PBL tidak lepas dari tantangan. Keterbatasan waktu pelajaran IPS yang hanya tiga hingga empat jam per minggu, beban administrasi guru, serta kurangnya sarana di daerah pedesaan menjadi kendala utama. Data Jurnal Pendidikan Sosial (2021) mencatat tingkat kegagalan PBL di sekolah menengah mencapai 35%.
Solusinya bisa dilakukan melalui integrasi proyek ke kegiatan ekstrakurikuler, kemitraan dengan Dinas Lingkungan Hidup, hingga pelatihan guru secara daring melalui platform Merdeka Mengajar. Pendekatan gamifikasi atau lomba proyek lingkungan tingkat kabupaten juga bisa meningkatkan antusiasme siswa tanpa menambah beban kurikulum.
Perencanaan pembelajaran IPS berbasis proyek di SMP merupakan strategi transformatif untuk menjadikan siswa sebagai agen perubahan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan poin ke-13 tentang aksi iklim. Keberhasilannya bergantung pada dukungan institusional: mulai dari alokasi anggaran, penyediaan pelatihan guru yang berkelanjutan, hingga revisi kurikulum nasional yang lebih fleksibel.
Dengan komitmen bersama antara guru, sekolah, pemerintah, dan masyarakat, pendidikan IPS berbasis proyek dapat melahirkan generasi muda Indonesia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berjiwa ekologis, berempati sosial, dan siap menghadapi tantangan global dengan semangat keberlanjutan.