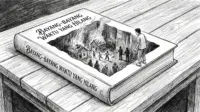Regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, merepresentasikan upaya legislatif yang berorientasi pada deregulasi struktural birokrasi, optimalisasi iklim investasi, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah mengartikulasikan bahwa regulasi tersebut akan menciptakan ekspansi kesempatan kerja, memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban tenaga kerja, serta menarik investasi asing melalui fleksibilitas rezim ketenagakerjaan yang lebih adaptif.
Namun, sejak tahap awal formulasi, kebijakan ini mendapat resistensi kuat dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk organisasi buruh, akademisi, mahasiswa, dan LSM. Regulasi ini memang menjanjikan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kesempatan kerja dan penguatan hak tenaga kerja. Namun, dalam aspek ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja secara khusus menyoroti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), atau yang umum dikenal sebagai kontrak kerja sementara.
PKWT didefinisikan sebagai bentuk hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dalam jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan yang tidak bersifat permanen. Transformasi dalam kerangka hukum ini, yang sebelumnya diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003, mengalami perubahan signifikan melalui PP No. 35 Tahun 2021 yang memperpanjang masa kontrak maksimal dari tiga tahun menjadi lima tahun.
Bahkan dalam rancangan awal UU Cipta Kerja, batas waktu kontrak sempat dihilangkan, menyerahkan pengaturannya sepenuhnya kepada peraturan pemerintah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kontrak kerja indefinit, atau kontrak kerja tanpa batas waktu yang berpotensi merugikan pekerja.
Restrukturisasi rezim PKWT yang diklaim memberikan fleksibilitas operasional, justru menimbulkan ambiguitas hukum dan ketidakpastian yang berdampak besar terhadap kesejahteraan pekerja. Dengan dihapusnya batasan jenis pekerjaan yang dapat diatur melalui PKWT serta diperpanjangnya durasi kontrak, terjadi pergeseran signifikan dalam jaminan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.
Fenomena ini menciptakan kondisi yang disebut sebagai “kasualisasi tenaga kerja”, di mana pekerjaan tetap berubah menjadi kontrak jangka pendek yang tidak memberikan kepastian karier bagi para pekerja. Di sisi lain, frasa “kebutuhan hidup layak” yang sebelumnya menjadi patokan dalam perhitungan upah minimum telah dihapus.
Kini, penetapan upah minimum hanya berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP), tanpa mempertimbangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota maupun Sektoral, yang selama ini memberikan perlindungan kontekstual sesuai kondisi lokal.
Ironisnya, regulasi yang digadang-gadang akan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, justru menampilkan wajah gelap pembangunan yang mengorbankan keadilan sosial dan hak-hak pekerja. Durasi PKWT yang diperpanjang menjadi lima tahun serta perluasan jenis pekerjaan yang dapat dikontrak menyebabkan pekerja terjebak dalam sistem kerja yang tidak pasti dan tidak manusiawi.
Pembangunan nasional yang sejati semestinya berpijak pada prinsip inklusivitas, tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, namun juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Sayangnya, UU Cipta Kerja malah menyesuaikan regulasi ketenagakerjaan dengan tuntutan globalisasi yang lebih mengutamakan efisiensi dan daya saing dibandingkan perlindungan pekerja.
Wajah kelam dari implementasi PKWT terlihat jelas dalam studi kasus PT MD di Kota Medan. Di perusahaan ini, formulasi PKWT dilakukan secara sepihak tanpa pelibatan pekerja, sehingga isi kontrak cenderung hanya menguntungkan pengusaha.
Praktik semacam ini mencerminkan ketimpangan struktural yang difasilitasi oleh kelemahan regulasi. Pekerja terpaksa menerima kontrak yang tidak adil karena keterbatasan pilihan kerja dan desakan ekonomi.
Mereka bahkan tidak berani menegosiasikan klausul merugikan karena takut tidak diterima bekerja. Ketidakseimbangan posisi tawar ini menunjukkan bagaimana kerentanan ekonomi dimanfaatkan oleh pemilik modal yang memanfaatkan fleksibilitas hukum untuk keuntungan sendiri.
Kasus ini merepresentasikan wajah gelap pembangunan yang ditopang oleh regulasi permisif dan pengawasan pemerintah yang lemah. Alih-alih menjadi instrumen perlindungan, hukum justru digunakan untuk melanggengkan ketidakadilan struktural. Hal ini tidak hanya merugikan secara individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam pembangunan nasional yang seharusnya mengedepankan kesejahteraan kolektif.
Lebih lanjut, UU Cipta Kerja juga menghapus sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar upah sesuai regulasi, mengurangi hak cuti panjang, dan memodifikasi ketentuan pesangon yang sebelumnya menjadi jaring pengaman finansial pasca-PHK. Dalam konteks ini, pekerja PKWT juga konsisten menerima remunerasi lebih rendah dibandingkan pekerja tetap, memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi.
Komnas HAM menilai UU Cipta Kerja sebagai kemunduran dalam perlindungan hak pekerja, bertentangan dengan prinsip progressive realization dalam pemenuhan hak sosial dan ekonomi. Serikat pekerja pun mengalami pelemahan signifikan karena UU ini menghilangkan kewajiban negosiasi dalam proses PHK. Padahal, keberadaan serikat pekerja menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pengusaha dan pekerja.
Alih-alih memperbaiki kualitas kerja, UU Cipta Kerja justru memperbesar pasar kerja informal yang rentan dieksploitasi. Akibatnya, rezim PKWT yang diusung menjadi paradoks kebijakan yang mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan hak asasi dan keadilan sosial.
Kemajuan ekonomi tanpa keadilan sosial adalah kemajuan semu. Kebijakan yang menyampingkan martabat manusia hanya akan melahirkan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Indonesia membutuhkan regulasi ketenagakerjaan yang tidak hanya kompetitif di mata investor, tetapi juga adil dan manusiawi bagi seluruh pekerja.
REFERENCES:
- Andriani, S. (2023). Transformasi kebijakan upah minimum di era UU Cipta Kerja. Jakarta: Penerbit Ekonomi Indonesia.
- ANTARA News. (2025, Mei 5). BPS: Proporsi pekerja informal di Indonesia naik 59,40 persen. https://www.antaranews.com/berita/4814169/bps-proporsi-pekerja-informal-di-indonesia-naik-5940-persen
- Bisnis.com. (2024, November 5). BPS: Jumlah Pekerja Informal Tetap Tinggi Meski Pekerja Formal Melonjak. https://ekonomi.bisnis.com/read/20241105/12/1813508/bps-jumlah-pekerja-informal-tetap-tinggi-meski-pekerja-formal-melonjak
- Geby Aviqa, S., Sunarmi, S., Leviza, J., & Harianto, D. (2025). Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Alih Daya (Studi Perjanjian Kerja Pada PT. MD di Kota Medan). AL-SULTHANIYAH, 14(1), 69–76. https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/download/3573/2599/
- Hartono, S. (2023). PKWT sebagai konstruksi juridis hubungan kerja terbatasi. Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia, 5(2), 115–129.
- Indraswari, L. (2020). Casualization of labor: Fenomena prekarisasi kerja di Indonesia. Bandung: ITB.
- Komnas HAM. (2021). Kajian UU Cipta Kerja dari perspektif hak asasi manusia. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Komnas HAM. (2021). Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. https://www.komnasham.go.id/files/20210428-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-dalam-$8CKM.pdf
- Kusuma, A. (2024). Dampak psikologis ketidakpastian kerja pada pekerja kontrak. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kusumawati, D. (2023). Penguatan pengawasan ketenagakerjaan di era fleksibilitas. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan.
- Maharani, P. (2024). Analisis kebijakan upah dan kesenjangan ekonomi. Jakarta: LIPI Press.
- Nugroho, T. (2020). Perubahan ruang lingkup PKWT dalam UU Cipta Kerja. Jakarta: Gramedia.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Permana, A. (2022). Transformasi durasi PKWT: Analisis yuridis PP 35/2021. Jakarta: Sinar Grafika.
- Podungge, I. P., Patiolo, D., & Silvya, V. (2021). Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang Dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja/Buruh. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(5), 387–397. https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/51/31/272
- Pozzoli, D., & Jahn, E. (2013). The wage penalty of temporary employment contracts. Berlin: Institute for Labor Economics.
- Pratama, R. (2020). Dampak UU Cipta Kerja terhadap kesejahteraan pekerja. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Pratiwi, S. (2021). Peran serikat pekerja dalam era UU Cipta Kerja. Jakarta: Trade Union Rights Centre.
- Putri, A. (2024). Social protection untuk pekerja informal dan kontrak. Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance.
- Rahman, F. (2025). Strategi edukasi hak pekerja di era digital. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Rahayu, S. (2020). Konsep kebutuhan hidup layak dalam kebijakan pengupahan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rastika, N. (2021). Efek UU Cipta Kerja terhadap fleksibilitas ketenagakerjaan. Jurnal Kebijakan Publik, 12(4), 213–227.
- Sari, C. M. (2025). Tantangan Implementasi PKWT di Lapangan Indonesia. https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/download/7904/6108/16603
- Sari, M., & Wijaya, K. (2021). Analisis perubahan ketentuan PKWT. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Schinder Law Firm. (2025, Juni 5). The Duration of Fixed-Term Employment Contracts in The Omnibus Law: from 3 Years to 5 Years. https://schinderlawfirm.com/blog/the-duration-of-fixed-term-employment-contracts-in-the-omnibus-law-from-3-years-to-5-years/
- Setiawan, H. (2024). Segmentasi pasar tenaga kerja Indonesia. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Sukma, R. (2021). Hak cuti dan kesejahteraan pekerja. Jakarta: UI.
- Sumardi, L., Dewi, K., & Santoso, B. (2020). Resistensi masyarakat sipil terhadap UU Cipta Kerja. Jakarta: Institute for Policy Research and Advocacy.
- Suryanto, E. (2025). Mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardani, L. (2025). Asimetri informasi dalam hubungan industrial Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Zubaidah, F., Rahman, A., & Pratama, D. (2021). Analisis yuridis klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Jakarta: Rajawali.
- Zubi, M., Rasyid, A., & Ningsih, R. (2020). Pasal-Pasal Kontroversial Terkait Hak-Hak Pekerja dalam UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 (Omnibus Law). Jurnal Hukum Keluarga, 1(1), 1–10. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/970/1007