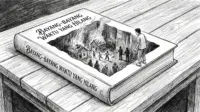Pernahkah kamu merasa jantung berdetak lebih cepat saat membuka email dari atasan? Atau merasakan mual setiap Senin pagi menjelang masuk kantor? Jika ya, besar kemungkinan kamu sedang berada dalam lingkungan kerja yang toxic.
Lingkungan kerja toxic bukan sekadar tumpukan tugas atau tenggat waktu yang mepet. Ia jauh lebih dalam. Tempat kerja yang toxic adalah ruang di mana konflik, ketidakadilan, dan tekanan psikologis menjadi santapan harian (Frost, 2003). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak kesehatan fisik maupun mental.
Apa Itu Lingkungan Kerja Toxic?
Menurut Kuschel dan Leung (2012), tempat kerja dikatakan toxic jika menunjukkan karakteristik seperti:
- Atasan yang manipulatif atau otoriter
- Rekan kerja yang saling menjatuhkan
- Minimnya apresiasi atau umpan balik positif
- Beban kerja yang tidak realistis
- Budaya lembur tanpa batas
Dampaknya tidak bisa dianggap enteng. Penelitian Maslach dan Leiter (2016) menunjukkan bahwa paparan lingkungan kerja yang buruk secara terus-menerus bisa menyebabkan burnout, kelelahan kronis, insomnia, bahkan gangguan kecemasan.
Bertahan atau Resign?
Pertanyaan ini tidak punya satu jawaban pasti. Setiap orang memiliki konteks hidup yang berbeda—mulai dari kondisi finansial, tanggung jawab keluarga, hingga kesiapan mental. Jika resign belum memungkinkan, maka bertahan dengan strategi yang sehat dan terukur bisa menjadi opsi jangka pendek yang bijak.
Strategi Bertahan di Lingkungan Kerja Toxic
1. Tetapkan Batasan Sehat (Personal Boundaries)
Teori batas pribadi dari Cloud dan Townsend (1992) menekankan pentingnya membedakan mana yang menjadi tanggung jawab kita dan mana yang bukan. Menetapkan batas emosional dan fisik dapat mencegah kita larut dalam dinamika toksik.
Contohnya: tidak membalas pesan kerja di luar jam kantor atau menolak tugas tambahan yang tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaan.
“Boundaries define us. They define what is me and what is not me.” – Cloud & Townsend (1992)
2. Bangun Dukungan Sosial
Menurut Social Support Theory (Cohen dan Wills, 1985), dukungan sosial dapat membantu menurunkan dampak stres melalui dua cara:
- Direct effect, yaitu meningkatkan kesejahteraan secara umum
- Buffering effect, yaitu melindungi kita saat menghadapi tekanan berat
Mencari teman kerja yang suportif, bergabung dalam komunitas profesi, atau sekadar punya tempat berbagi cerita bisa menjadi “vitamin mental” yang esensial.
3. Terapkan Coping Strategy Aktif
Lazarus dan Folkman (1984) membagi strategi coping menjadi dua:
- Problem-focused coping, yaitu menghadapi masalah secara langsung
- Emotion-focused coping, yaitu mengelola respons emosional terhadap masalah
Contoh coping aktif antara lain: menyusun jadwal kerja yang realistis, berdiskusi dengan HR, atau mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
Penelitian Fitriani dan Ardyan (2021) menyebutkan bahwa coping aktif secara signifikan mengurangi keinginan untuk resign di lingkungan kerja yang toxic.
4. Gunakan Cognitive Reframing
Dalam psikologi kognitif, teknik cognitive reframing membantu kita melihat situasi negatif dari sudut pandang yang lebih konstruktif (Seligman, 2011). Misalnya, rekan kerja yang terlalu kritis bisa diposisikan sebagai “pelatih mental” yang melatih ketahanan dan komunikasi asertif kita.
5. Latih Self-Compassion
Menurut Neff (2003), self-compassion adalah sikap penuh kasih terhadap diri sendiri, terutama di saat-saat sulit. Dengan memiliki welas asih terhadap diri sendiri, kita tidak mudah menyalahkan diri ketika menghadapi tekanan, sekaligus menjaga stabilitas psikologis.
6. Praktikkan Mindfulness dan Relaksasi
Mindfulness menurut Kabat-Zinn (2003) adalah kesadaran penuh terhadap saat ini. Latihan seperti meditasi, pernapasan dalam, atau menulis jurnal dapat membantu meredakan stres sesaat dan menstabilkan emosi di tengah tekanan kerja yang intens.
Kalau Memilih Resign, Ini Langkah Aman
Mengundurkan diri bukan berarti kamu lemah. Justru, bisa jadi itu langkah paling rasional dan berani demi melindungi dirimu dari kehancuran yang lebih besar. Berikut beberapa langkah yang disarankan sebelum resign:
- Siapkan dana darurat minimal 3–6 bulan gaji
- Cari pekerjaan baru atau susun rencana pasca-resign
- Beri pemberitahuan secara profesional minimal dua minggu sebelumnya
- Jaga etika—tinggalkan tempat kerja dengan elegan dan tidak membakar jembatan
Penutup
Keputusan untuk bertahan atau resign tidak sesederhana benar atau salah. Yang paling penting adalah kemampuan mengenali diri sendiri dan kebutuhan hidupmu saat ini. Bila memilih bertahan, pastikan kamu punya strategi bertahan yang matang dan dukungan yang cukup. Namun jika kamu merasa sudah melampaui batas toleransi, mungkin inilah saatnya membuka lembaran baru yang lebih sehat dan manusiawi.
Ingatlah, kesehatan mental tidak bisa ditukar dengan gaji sebesar apa pun.
Daftar Pustaka
- Cloud, H., & Townsend, J. (1992). Boundaries: When to Say Yes, How to Say No to Take Control of Your Life. Zondervan.
- Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98(2), 310–357.
- Frost, P. J. (2003). Toxic Emotions at Work: How Compassionate Managers Handle Pain and Conflict. Harvard Business Review Press.
- Kuschel, K., & Leung, A. (2012). Toxic Workplace Environment: A Guide to Understanding and Handling Toxic Behavior. Journal of Business and Management Research, 1(1), 22–30.
- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). Burnout: A Multidimensional Perspective. Psychology Press.
Neff, K. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223–250. - Purba, D. E., & Aisyah, S. (2020). Hubungan antara dukungan sosial dan stres kerja pada karyawan. Jurnal Psikologi, 16(2), 101-110.
- Fitriani, L., & Ardyan, E. (2021). Dampak lingkungan kerja toxic terhadap turnover intention karyawan. Jurnal Manajemen Indonesia, 21(1), 45-55.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. Springer.
- Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. Free Press.
- Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 144–156.