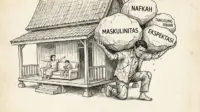Suku Jawa merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia dengan kekayaan adat dan tradisi yang tetap terjaga hingga saat ini. Salah satu tradisi yang masih lestari adalah ruwatan anak dengan media wayang kulit.
Tradisi ini dipercaya masyarakat Jawa sebagai penolak bala, mengandung nilai luhur tentang harmoni hidup, keselarasan alam, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Namun, di tengah arus modernisasi, praktik ruwatan menghadapi berbagai tantangan yang mengancam kelestariannya.
Ruwatan dalam bahasa Jawa berarti “dilepas” atau “dibebaskan”. Secara keseluruhan, ruwatan adalah upacara adat yang bertujuan untuk membebaskan seseorang dari kesialan atau kutukan yang dianggap membawa bahaya.
Tradisi ini berkaitan dengan mitologi Jawa tentang Batara Kala, putra Batara Guru yang digambarkan sebagai raksasa. Dalam legenda, Batara Kala meminta makanan berupa manusia yang dikategorikan sebagai wong sukerto atau orang yang dianggap memiliki kesialan.
Untuk menghindari ancaman Batara Kala, masyarakat Jawa melakukan ruwatan dengan pagelaran wayang kulit, memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Banyak masyarakat Jawa percaya bahwa jika seseorang yang termasuk kategori wong sukerto tidak diruwat, maka ia akan mengalami berbagai bentuk kesialan. Beberapa di antaranya adalah hidup sengsara dengan rezeki seret, usaha gagal, atau sering mengalami kesulitan hidup.
Selain itu, ada keyakinan bahwa seseorang bisa mengalami penyakit yang sulit disembuhkan meski telah diobati secara medis. Beberapa mitos juga menyebutkan bahwa mereka yang tidak menjalani ruwatan dapat mengalami gangguan mental. Kepercayaan paling ekstrem menyebutkan bahwa seseorang bisa mengalami kematian jika tidak diruwat.
Ruwatan tidak dilakukan sembarangan, melainkan hanya untuk mereka yang termasuk dalam kategori wong sukerto. Beberapa kategori yang harus menjalani ruwatan antara lain anak tunggal laki-laki yang disebut ontang-anting, anak tunggal perempuan yang disebut unting-unting, serta anak yang lahir dalam urutan tertentu seperti gedhana-gedhini (anak pertama laki-laki, kedua perempuan), uger-uger lawang (dua anak laki-laki), dan kembar sepasang (dua anak perempuan).
Selain itu, anak yang lahir dalam kondisi tertentu seperti pendhawa (lima anak laki-laki), gotong mayit (tiga anak perempuan semua), cukil dulit (tiga anak laki-laki semua), julung sungsang (lahir di tengah hari), dan margana (lahir saat ibu dalam perjalanan) juga dianggap memerlukan ruwatan.
Dalam praktiknya, ruwatan anak dilakukan dengan serangkaian ritual khusus yang melibatkan pagelaran wayang kulit. Keluarga yang ingin mengadakan ruwatan harus mengundang seorang dalang ke sanggar seni.
Selain itu, mereka juga harus menyiapkan sesajen yang diperlukan, meliputi jajan pasar, bunga setaman, tumpeng, panggang ayam, jarik batik, dan berbagai perlengkapan lainnya. Dalam puncak acara, dalang membawakan kisah Batara Kala yang ingin memangsa anak-anak wong sukerto.
Di tengah pertunjukan, anak yang diruwat dimandikan dengan air bunga setaman sebagai simbol penyucian. Ritual ini diakhiri dengan pembakaran dupa, yang konon akan menimbulkan rasa lelah seolah sedang dikejar oleh sesuatu, melambangkan pelepasan kesialan.
Sebagai bagian dari budaya Jawa, ruwatan mendapat perhatian dari pemerintah. Upaya yang telah dilakukan untuk melestarikan tradisi ini antara lain pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh Kemendikbudristek sejak 2013.
Selain itu, pemerintah memberikan dukungan hibah dan pelatihan bagi dalang wayang kulit agar tradisi ini tetap hidup. Beberapa sekolah dan perguruan tinggi di Jawa juga mengadakan workshop ruwatan untuk mengenalkan tradisi ini kepada generasi muda. Namun, meskipun mendapat dukungan dari berbagai pihak, ruwatan masih menghadapi tantangan besar.
Seiring berkembangnya zaman, tradisi ruwatan menghadapi berbagai tantangan, terutama dari gempuran budaya modern. Generasi muda lebih tertarik pada budaya populer seperti film dan musik dari luar negeri, sehingga kurang mengenal tradisi ini.
Selain itu, perubahan pandangan masyarakat membuat sebagian orang merasa bahwa ruwatan tidak lagi relevan di era modern. Beberapa menganggapnya sebagai kepercayaan kuno yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
Tantangan lainnya adalah minimnya regenerasi dalang yang menguasai ruwatan wayang kulit. Jumlah dalang yang memahami ritual ini semakin berkurang karena kurangnya minat generasi muda untuk meneruskan profesi ini.
Untuk menjaga kelestarian ruwatan, diperlukan upaya lebih lanjut, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Edukasi kepada generasi muda sangat penting agar mereka memahami nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini.
Selain itu, perlu dilakukan inovasi agar ruwatan dapat tetap relevan dengan perkembangan zaman, misalnya dengan memanfaatkan media digital untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi tentang ruwatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tradisi ruwatan dapat terus hidup dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Jawa.
Ruwatan bukan sekadar ritual, melainkan cerminan nilai-nilai kearifan lokal Jawa yang mengajarkan harmoni dengan alam dan sesama. Meski berada di tengah arus modernisasi, tradisi ini tetap memiliki makna mendalam bagi masyarakat Jawa. Upaya pelestarian dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar budaya ini tetap bertahan di tengah perkembangan zaman.