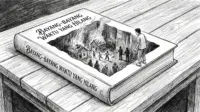Abstrak
Teori Spiral of Silence menjelaskan bagaimana individu cenderung menyembunyikan pendapatnya ketika merasa pandangannya bertentangan dengan opini mayoritas. Di era digital, media sosial menjadi arena baru bagi ekspresi pendapat, namun justru memperkuat fenomena keengganan berpendapat karena ancaman isolasi sosial kini muncul dalam bentuk digital: cibiran, perundungan daring, atau pembatalan (cancel culture). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana keengganan berpendapat terjadi di media sosial dan bagaimana teori Spiral of Silence masih relevan di tengah keterbukaan komunikasi daring. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui survei dan wawancara singkat terhadap 30 pengguna aktif media sosial, ditemukan bahwa mayoritas responden menahan diri untuk menyuarakan opini pribadi yang kontroversial, terutama menyangkut isu agama, politik, dan gender. Mekanisme spiral diam ini tetap bekerja, bahkan diperkuat oleh algoritma media sosial dan dinamika opini viral. Artikel ini merefleksikan pentingnya literasi digital dan keberanian berpendapat sebagai bentuk resistensi terhadap tekanan mayoritas digital.
Kata kunci: Spiral of Silence, media sosial, opini publik, keengganan berpendapat, cancel culture
Abstract
The Spiral of Silence theory explains how individuals tend to hide their opinions when they feel their views are at odds with the majority opinion. In the digital era, social media has become a new arena for the expression of opinions, but it actually strengthens the phenomenon of reluctance to express opinions because the threat of social isolation now appears in digital form: ridicule, online bullying, or cancellation (cancel culture). This research aims to identify the extent to which reluctance to express opinions occurs on social media and how the Spiral of Silence theory is still relevant amidst open online communication. Using a qualitative descriptive approach through surveys and short interviews with 30 active social media users, it was found that the majority of respondents refrained from voicing controversial personal opinions, especially regarding religious, political and gender issues. This silent spiral mechanism still works, even reinforced by social media algorithms and viral opinion dynamics. This article reflects the importance of digital literacy and the courage to express opinions as a form of resistance to the pressure of the digital majority.
Keywords: Spiral of Silence, social media, public opinion, reluctance to express opinions, cancel cultureArticle History:
Pendahuluan
Media sosial telah menjadi ruang publik yang sangat aktif dalam dinamika kehidupan modern. Platform seperti X (dulu Twitter), Instagram, Facebook, dan TikTok menawarkan ruang terbuka bagi masyarakat untuk berdiskusi, menyampaikan opini, serta merespons isu sosial, politik, dan budaya. Namun, kebebasan ini ternyata membawa paradoks: semakin luas ruang berpendapat, semakin besar pula tekanan sosial yang dirasakan.
Fenomena ini sangat relevan jika ditinjau dari teori Spiral of Silence yang pertama kali dikemukakan oleh Elisabeth Noelle-Neumann pada 1974. Menurut teori ini, seseorang cenderung menghindari menyuarakan opini yang dianggap berbeda atau bertentangan dengan opini mayoritas karena takut mengalami isolasi sosial. Dalam konteks era digital, bentuk isolasi tersebut kini bermanifestasi dalam bentuk komentar negatif, cyberbullying, hingga cancel culture.
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Spiral of Silence tetap eksis, bahkan semakin diperkuat dalam ekosistem media sosial. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara lebih mendalam pengalaman dan persepsi pengguna media sosial terkait keengganan mereka dalam menyuarakan pendapat yang berbeda dari arus utama.
Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena keengganan berpendapat. Metode ini memungkinkan eksplorasi terhadap pengalaman subjektif individu, motivasi personal, serta konteks sosial yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam menyampaikan opini secara publik di media sosial.
Pengumpulan Data
Data diperoleh melalui dua teknik utama:
- Survei daring terbuka yang disebarkan melalui Google Form, dengan 30 responden berusia 18–35 tahun. Mereka dipilih secara purposive sampling berdasarkan keaktifan mereka dalam menggunakan media sosial dan keterlibatan dalam diskusi publik.
- Wawancara semi-terstruktur secara daring melalui Zoom dan WhatsApp call untuk menggali lebih dalam alasan dan pengalaman mereka dalam menyuarakan atau menyembunyikan opini.
Pertanyaan yang diajukan mencakup:
- Apakah Anda pernah merasa enggan menyuarakan pendapat di media sosial?
- Apa yang menjadi alasan utama dari keengganan tersebut?
- Apakah Anda pernah mendapatkan reaksi negatif setelah menyuarakan opini?
- Bagaimana peran teman, keluarga, atau komunitas dalam memengaruhi keputusan Anda?
Analisis Data
Analisis dilakukan dengan analisis tematik, mengidentifikasi pola, tema, dan kategori seperti: ketakutan akan isolasi, persepsi terhadap opini mayoritas, dan tekanan sosial digital. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan konfirmasi ulang kepada responden untuk memastikan akurasi interpretasi.
Hasil dan Pembahasan
1. Ketakutan terhadap Reaksi Negatif
Sebanyak 83% responden menyatakan bahwa mereka merasa enggan menyuarakan opini ketika topik yang dibahas bersifat sensitif. Isu politik, agama, dan gender menjadi topik yang paling dihindari. Ketakutan yang muncul bukan hanya bersifat personal, tetapi juga sosial: takut dikucilkan, kehilangan pertemanan, bahkan kehilangan pekerjaan.
Salah satu responden mengatakan:
“Saya pernah membuat status soal kebijakan pemerintah, dan langsung banyak yang menyerang, bahkan dari teman kuliah. Setelah itu saya hapus dan tidak pernah lagi posting topik serupa.”
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial menyediakan fitur untuk berbicara bebas, tekanan sosial tetap menjadi faktor pembungkam yang kuat.
2. Dampak Psikologis dan Strategi Bertahan
Beberapa responden mengaku mengalami tekanan psikologis setelah menyuarakan opini yang berbeda. Beberapa memilih untuk:
- Menghapus unggahan
- Menonaktifkan komentar
- Membatasi akses hanya untuk teman tertentu
- Tidak aktif di media sosial untuk sementara waktu
Diam menjadi bentuk resistensi pasif dan mekanisme perlindungan diri.
3. Peran Cancel Culture
Cancel culture muncul sebagai bentuk isolasi digital yang paling menakutkan. Ketika seseorang menyuarakan opini yang bertentangan, mereka bisa mengalami pembatalan: dikucilkan, dikecam massal, bahkan diboikot secara sosial dan ekonomi.
Seorang responden menyatakan:
“Saya tahu seseorang yang dipecat karena unggahannya tentang isu gender yang kontroversial. Saya tidak ingin mengalami hal yang sama.”
Fenomena ini memperkuat Spiral of Silence karena mendorong pengguna untuk memprioritaskan kenyamanan sosial daripada menyuarakan kebenaran versi mereka.
4. Algoritma Media Sosial dan Ilusi Konsensus
Platform media sosial juga memperkuat fenomena ini. Algoritma cenderung mengangkat konten yang mendapat banyak interaksi positif, sehingga pendapat yang berbeda atau tidak populer sering kali tidak terlihat.
Ilusi bahwa mayoritas memiliki opini seragam menjadi semakin kuat karena:
- Opini yang disukai tampil lebih sering
- Konten yang memicu emosi mendapat lebih banyak eksposur
- Ulasan minoritas tenggelam atau bahkan disembunyikan
Akibatnya, banyak pengguna merasa bahwa pandangan mereka adalah minoritas ekstrem, padahal mungkin saja pandangan tersebut lebih luas dari yang tampak.
Diskusi: Tantangan dan Peluang
Fenomena Spiral of Silence di media sosial menimbulkan pertanyaan penting tentang masa depan kebebasan berpendapat. Apakah ruang digital yang awalnya menjanjikan kebebasan kini justru mempersempit ruang diskusi?
Tantangan utama yang dihadapi antara lain:
- Rendahnya literasi digital, khususnya dalam membedakan kritik dengan serangan personal
- Kurangnya fasilitas moderasi diskusi yang adil dan inklusif
- Ketidakmampuan platform media sosial dalam mengakomodasi opini beragam tanpa menciptakan konflik destruktif
Namun, fenomena ini juga membuka peluang untuk membentuk pendekatan komunikasi yang lebih bijak dan tangguh. Dengan mendorong:
- Pendidikan kritis dan empatik di ruang digital
- Peningkatan keberanian berpendapat, terutama bagi generasi muda
- Desain algoritma yang lebih netral, yang tidak hanya mengedepankan viralitas, tetapi juga keberagaman perspektif
Kesimpulan
Penelitian ini membuktikan bahwa Spiral of Silence tetap hidup dan bahkan berkembang dalam lanskap media sosial. Ketakutan akan isolasi sosial dalam bentuk digital—baik berupa cibiran, perundungan, maupun pembatalan—mendorong banyak pengguna untuk memilih diam daripada menyuarakan kebenaran subjektif mereka.
Platform media sosial, yang semula digadang-gadang sebagai ruang demokratis, kini menjadi tempat di mana opini minoritas semakin terpinggirkan. Algoritma, dinamika viral, dan tekanan kelompok memperkuat kecenderungan untuk menghindari diskusi terbuka.
Untuk membangun ruang digital yang sehat, diperlukan:
- Literasi digital sebagai kemampuan dasar dalam bermedia sosial
- Keberanian untuk berbeda pendapat
- Desain sistem yang inklusif dan suportif, baik dari sisi teknis maupun budaya komunikasi
Dengan demikian, media sosial bisa kembali menjadi ruang dialog dan pertukaran ide yang menghormati perbedaan, bukan hanya tempat untuk menyuarakan opini yang aman secara sosial.
Referensi
- Gearhart, S., & Zhang, W. (2014). Gay bullying and the Spiral of Silence: Examining the use of opinion expression on social media. Social Science Computer Review, 32(1), 18–36.
- Noelle-Neumann, E. (1974). The Spiral of Silence: A theory of public opinion. Journal of Communication, 24(2), 43–51.
- Glynn, J.C. & McLeod, J. (1984). “Public opinion du jour: An examination of the spiral of silence, “ Public Opinion Quarterly 48 (4):731-740.
- Glynn, J.C., Hayes, F.A. & Shanahan, J. (1997). “Perceived support for ones opinions sand willingness to speak out: A meta-analysis of survey studies on the „spiral of silence‟” Public Opinion Quarterly 61 (3):452-463.
- Ho, S.S., Chen, V.H.H., & Sim, CC. (2013).The spiral of silence: examining how cultural predispositions, news attention, and opinion congruency relate to opinion expression.Asian journal of communication,23(2), 113-134.