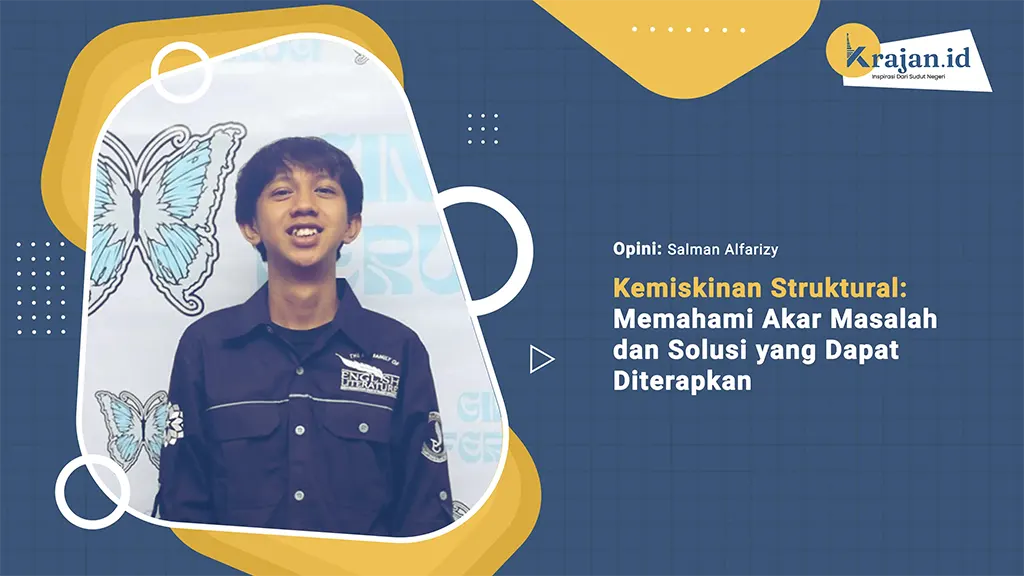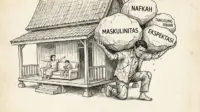Kemiskinan adalah masalah sosial yang telah mengakar di Indonesia selama beberapa dekade, menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, seperti program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Namun, tantangan tetap ada, terutama ketidakmerataan pembangunan antar wilayah dan kurangnya lapangan kerja yang layak. Dalam menghadapi masalah ini, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Dengan meningkatkan keterampilan masyarakat dan menciptakan peluang ekonomi yang inklusif, diharapkan angka kemiskinan dapat terus menurun sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 9,03 persen, setara dengan 25,22 juta jiwa. Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, angka ini tetap tinggi dan menunjukkan tantangan besar, terutama dalam mengatasi ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan.
Di perkotaan, angka kemiskinan mencapai 7,09 persen, sementara di perdesaan lebih tinggi, yaitu 11,79 persen. Hal ini menuntut strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan.
Namun, di balik angka-angka tersebut, ada dimensi lain yang lebih kompleks, yaitu kemiskinan struktural. Menurut Yousuf Daas dalam bukunya, kemiskinan struktural adalah kondisi di mana individu atau kelompok terjebak dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik yang tidak mendukung mereka untuk keluar dari kemiskinan.
Fenomena ini menciptakan “perangkap kemiskinan” yang sulit diatasi tanpa perubahan signifikan dalam kebijakan dan struktur yang ada. Kondisi ini sering diperparah oleh ketimpangan distribusi kekayaan dan kesempatan, terutama di wilayah pedesaan yang minim infrastruktur dan layanan dasar.
Baca Juga: Lulusan Sekolah Lebih Pilih Bekerja, Ini Kata BPS
Ketidakmampuan individu untuk mengakses pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sumber daya lain merupakan ciri utama dari kemiskinan struktural. Misalnya, petani tanpa lahan atau buruh tidak terampil sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan akibat keterbatasan pendidikan dan keterampilan.
Selain itu, diskriminasi sosial dan ekonomi juga memperburuk kondisi ini, membuat kelompok tertentu semakin terpinggirkan. Oleh karena itu, untuk memutus rantai kemiskinan struktural, diperlukan reformasi kebijakan yang adil, peningkatan akses terhadap pendidikan, serta program pelatihan keterampilan yang menyasar kelompok rentan.
Salah satu faktor lain yang memperburuk kemiskinan struktural adalah pola pikir masyarakat. Pandangan tradisional seperti “banyak anak banyak rezeki” sering kali mendorong keluarga untuk memiliki banyak anak dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan di masa depan.
Namun, kenyataannya, jumlah anak yang banyak justru menjadi beban ekonomi bagi keluarga dengan sumber daya terbatas. Keterbatasan ini membuat orang tua kesulitan memberikan pendidikan dan perawatan yang memadai.
Baca Juga: Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Memberantas Pungli di Samsat
Oleh karena itu, edukasi mengenai perencanaan keluarga dan pentingnya investasi dalam pendidikan anak sangat diperlukan. Dengan mengubah pola pikir ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami bahwa kualitas hidup lebih penting daripada jumlah anggota keluarga.
Dalam jangka panjang, upaya untuk mengatasi kemiskinan struktural harus dilakukan melalui pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak. Pemerintah perlu memastikan distribusi sumber daya yang adil, sementara sektor swasta dapat membantu menciptakan lapangan kerja yang inklusif.
Di sisi lain, masyarakat juga harus aktif berpartisipasi dalam program pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan meraih kehidupan yang lebih sejahtera.