Bukan karena kurang pintar seseorang bisa terjebak investasi bodong. Barangkali justru karena kita adalah makhluk sosial yang terlalu percaya pada mata telanjang pada wajah yang terlihat meyakinkan, pada suara yang terdengar akrab, dan pada komunitas yang terasa dekat di ruang digital.
Beberapa tahun terakhir, gairah masyarakat terhadap investasi terutama di bidang crypto dan saham meningkat tajam. Euforia itu membawa semangat baru: keinginan untuk “naik kelas” lewat instrumen keuangan modern.
Namun, di balik semangat tersebut, tersembunyi bayang-bayang gelap penipuan yang mengintai, dari skema Crypto Ponzi hingga bursa kloning. Semua menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa dasar aktivitas ekonomi yang jelas.
Pendekatan ekonomi neoklasik, yang selama ini mengandalkan rasionalitas individu, tampak tak mampu menjelaskan fenomena ini. Mengapa di era keterbukaan informasi, ketika data dan laporan keuangan mudah diakses, orang masih bisa tertipu? Jawabannya terletak pada sisi sosial manusia sebuah konteks yang dijelaskan oleh konsep embeddedness atau keterlekatan dalam sosiologi ekonomi.
Bayangkan, suatu hari kamu melihat promosi investasi di media sosial. Tampilannya profesional, narasinya persuasif, dan di baliknya ada seorang “influencer” yang seolah paham betul dunia finansial. Ia lalu mengarahkanmu bergabung dalam grup di Discord, WhatsApp, atau Telegram. Di sana, kamu disambut ramah, diberi “edukasi investasi”, bahkan diundang ikut membeli koin baru dengan janji “cuan berlipat dalam waktu dekat”.
Awalnya terasa masuk akal. Ada grafik, testimoni, dan tangkapan layar saldo yang meningkat. Hingga akhirnya, koin itu ambruk, platform lenyap, dan para admin grup menghilang. Namun menariknya, grup itu tak mati. Mereka tetap aktif, siap menjerat korban baru yang masih percaya pada narasi yang sama.
Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya jaringan sosial dalam membentuk kepercayaan. Di era digital, keputusan investasi tak lagi berdasar laporan OJK atau analisis fundamental, melainkan rasa percaya terhadap figur atau komunitas yang dianggap “sejalan”.
Konsep embeddedness pertama kali diperkenalkan Karl Polanyi dalam The Great Transformation. Ia berpendapat, tindakan ekonomi manusia tidak pernah benar-benar berdiri sendiri, melainkan terikat dalam konteks sosial. Mark Granovetter kemudian mengembangkan ide itu, menegaskan bahwa norma, kepercayaan, dan relasi sosial menjadi pondasi utama keputusan ekonomi.
Analogi sederhana: selembar uang Rp100.000 tak memiliki nilai apa pun tanpa kepercayaan bersama bahwa kertas itu bisa ditukar dengan barang atau jasa. Nilai ekonomi, dengan demikian, dibangun dari kesepakatan sosial, bukan hanya angka.
Dalam dunia investasi digital, influencer finansial menjadi figur sentral. Mereka tampil santai, berbicara seperti teman, menggunakan gaya bahasa sehari-hari: “Gue nggak ngajarin kaya, cuma sharing pengalaman aja.” Kalimat seperti itu menciptakan kesan keakraban dan menumbuhkan rasa percaya.
Padahal, hubungan yang terbangun bersifat parasosial hubungan satu arah di mana audiens merasa dekat dengan figur publik yang sebenarnya tak mengenal mereka. Saat kepercayaan ini terbentuk, apa pun yang dikatakan influencer lebih dipercaya dibanding laporan keuangan resmi. Ketika ia berkata, “Aku coba platform ini, hasilnya lumayan nambah cuan,” banyak orang akan mengikutinya tanpa berpikir panjang.
Kepercayaan yang lahir dari kedekatan semu itu sering kali lebih kuat daripada data atau logika. Seorang investor pemula lebih mudah percaya pada screenshot keuntungan teman ketimbang laporan fundamental sebuah aset. Mengapa? Karena manusia cenderung mempercayai sesuatu yang terasa nyata secara sosial dibanding sesuatu yang abstrak secara statistik.
Di luar pengaruh individu, ada pula kekuatan komunitas digital. Grup-grup di WhatsApp, Telegram, atau Discord menjadi ruang di mana norma ekonomi baru terbentuk. Di sana muncul istilah seperti HODL (Hold On Dear Life), yang berarti menahan aset meskipun nilainya anjlok. Norma seperti ini mengajarkan keberanian semu, bahkan mendorong perilaku spekulatif.
Para anggota saling meneguhkan keputusan masing-masing, menciptakan atmosfer optimisme yang terkadang menafikan realitas pasar. Inilah bentuk lain keterlekatan sosial: ketika keputusan ekonomi bukan lagi hasil analisis pribadi, melainkan cerminan dari tekanan atau solidaritas kelompok.
Ada pula unsur psikologis yang memperkuat fenomena ini: FOMO (Fear of Missing Out). Laporan OJK menyebut FOMO sebagai salah satu pemicu utama generasi muda terjebak investasi bodong. Rasa takut tertinggal membuat banyak orang terburu-buru menanam uang tanpa riset. Mereka takut kehilangan peluang yang belum tentu nyata, namun tidak takut kehilangan uang yang benar-benar ada.
Logika ekonomi modern menuntut kita berpikir rasional menggunakan data, menganalisis risiko, dan memilih platform legal. Tapi logika sosial menggoda kita lewat keakraban, emosi, dan rasa percaya. Di titik ini, keduanya sering kali bertabrakan.
Kepercayaan sejatinya adalah bahan bakar utama dalam kehidupan sosial. Namun di tangan yang salah, ia bisa berubah menjadi alat manipulasi. Dalam jaringan sosial yang rapuh, kepercayaan mudah dibajak oleh pihak yang memahami cara kerja emosi manusia.
Mereka tahu bahwa manusia ingin merasa diterima dalam komunitas. Mereka tahu, testimoni lebih ampuh dari data. Mereka tahu, di dunia yang serba cepat, logika sering kalah oleh rasa. Akibatnya, banyak orang terjerumus bukan karena bodoh, melainkan karena kepercayaannya disalahgunakan.
Kita mungkin bisa memperkuat literasi finansial, memperbanyak edukasi, dan menegakkan regulasi. Namun selama rasa percaya masih bisa direkayasa melalui hubungan sosial semu, jebakan investasi bodong akan tetap menemukan jalannya.
Mungkin sudah saatnya kita belajar bukan hanya menjadi investor yang cerdas, tetapi juga menjadi manusia yang waspada terhadap manipulasi kepercayaan. Sebab dalam ekonomi modern yang berbasis relasi, kebijaksanaan tak hanya lahir dari angka, melainkan dari kemampuan mengenali siapa yang pantas dipercaya.


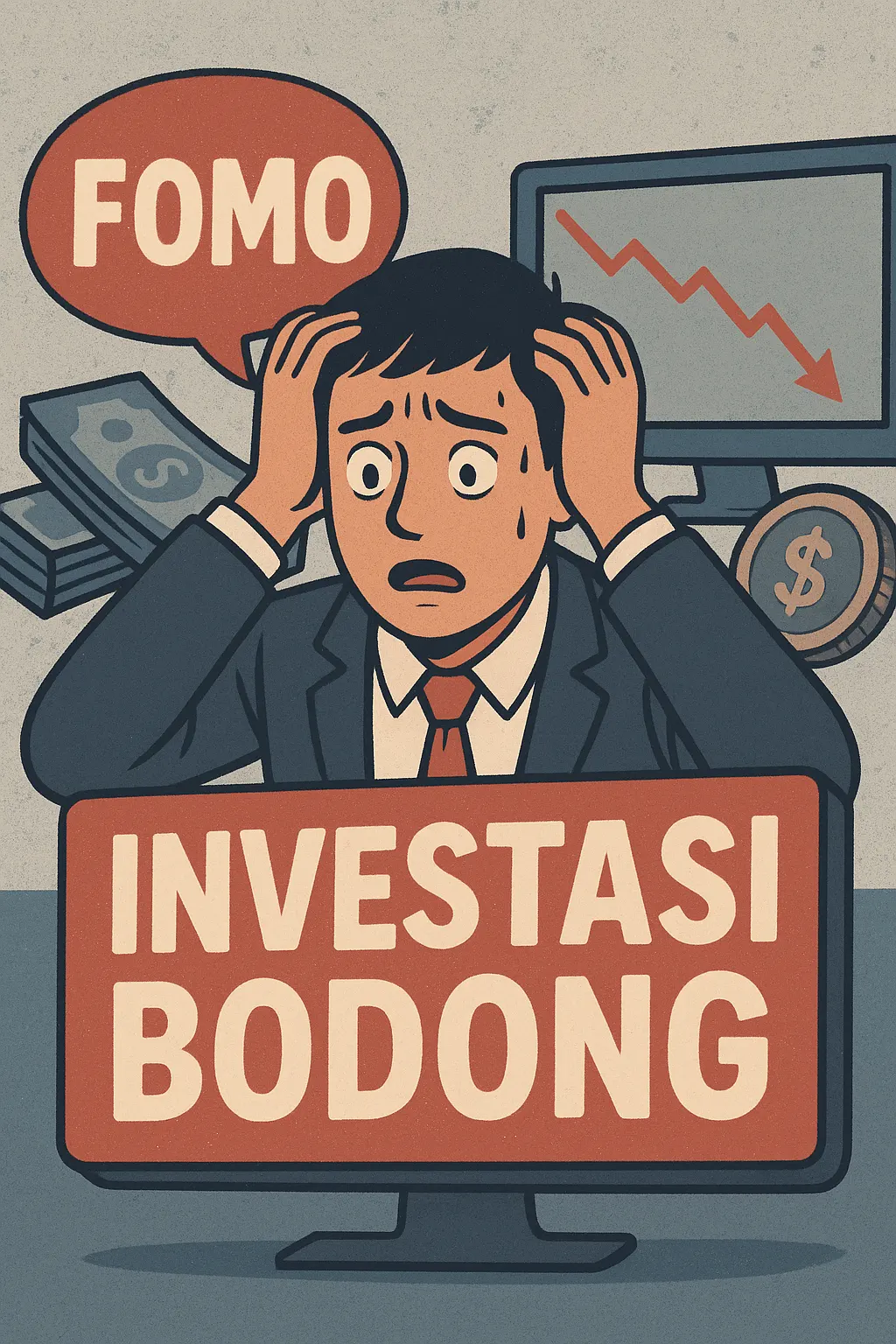






sangat informatif saya jadi pegen beli bitcoin