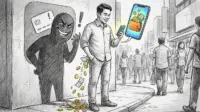Diskursus mengenai pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) masih menjadi topik hangat di berbagai ruang publik. Pro dan kontra mengemuka, terutama dari kalangan masyarakat sipil seperti organisasi perempuan, mahasiswa, dan aktivis muda. Banyak yang menilai revisi ini sebagai sinyal bangkitnya kembali militerisme dalam kehidupan sipil Indonesia.
Pertanyaannya kemudian muncul: jika Kartini masih hidup di masa sekarang, bagaimana ia akan merespons situasi ini? Apakah semangat yang ia kobarkan dahulu akan merestui sebuah tatanan sosial yang cenderung memusatkan kuasa pada struktur hierarkis militer?
Feodalisme, Musuh Besar Kartini
Ada beberapa alasan yang membuat saya yakin bahwa Kartini tidak akan menerima hasil putusan yang mengesahkan UU TNI. Yang pertama, Kartini sangat membenci feodalisme jawa. Kartini adalah pelopor sekaligus korban dari suatu sistem yang feodalistik.
Dalam surat-suratnya, Kartini banyak berbicara mengenai nilai-nilai tradisi, khususnya tradisi Jawa, yang cenderung membelenggu perempuan. Keterbelakangan tersebut akhirnya menjadikan perempuan sebagai kaum yang tidak berdaya dan ter-subordinasi.
Jika para penganut feodalisme menganggap gerakan Kartini merupakan gerakan perlawanan yang harus diberangus, militerisme Orde Baru menggunakan cara pandang yang sama untuk memberangus gerakan perempuan yang membawa ide-ide perlawanan Kartini.
Selama Soeharto berkuasa pada masa orde baru, Kartini tidak digambarkan sebagai seorang feminis yang memiliki keberpihakan pada pribumi, melainkan dicitrakan hanya sebagai tokoh emansipasi yang berjasa dalam menyetarakan pendidikan untuk dapat diakses oleh laki-laki dan perempuan. Itu saja.
Seremonial tahunan hari Kartini yang minim esensi, jarang sekali menceritakan bahwa mimpi besar Kartini telah menjadi inspirasi terbentuknya berbagai organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Dalam bukunya, Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia (2008, hlm. 87), Dr. Riant Nugroho menjelaskan bahwa seruan Kartini agar kaum muda membentuk suatu wadah persatuan, diwujudkan dengan terbentuknya Indische Vereeniging oleh para pemuda yang belajar di Belanda, yang akhirnya disebut Perhimpunan Indonesia. Disusul dengan berbagai macam organisasi perempuan yang terbentuk seperti Poetri Mardika (1912), Jong Java Meisjeskring (1915) dan Aisyiyah (1917).
Dengan dalih memberantas ancaman terhadap kedaulatan negara, Soeharto mengebiri semangat Kartini yang termanifestasi dalam berbagai gerakan perempuan saat itu. Soeharto mencabut gerakan kesetaraan tersebut hingga ke akarnya dan menggantinya dengan Dharma Wanita dan PKK, sebagai satu-satunya organisasi perempuan yang diizinkan oleh pemerintahan orba. Gerakannya didomestifikasi dari yang awalnya progresif, menjadi gerakan yang hanya fokus dalam mengurus rumah tangga.
Dari sini dapat kita simpulkan bahwa feodalisme dan militerisme memiliki irisan; sama-sama menekankan hierarki sosial dan kekuasaan yang didasarkan pada kekuatan golongan yang berkuasa.
Kemesraan antara Militerisme dan Kapitalisme
Yang kedua, Kartini memiliki konsep keberpihakan ekonomi kepada masyarakat sipil. Kartini tidak hanya memperjuangkan kesetaraan gender. Kartini, menghendaki masyarakat sipil agar menguasai alat produksi untuk kesejahteraan ekonomi mereka. Hal ini diwujudkan Kartini dalam usahanya memajukan perekonomian masyarakat Jepara melalui seni ukir.
Kartini memilih perajin yang berada di daerah Belakang Gunung, yang terletak di belakang Benteng Portugis. Penduduk tersebut dipilih karena kondisi mereka yang sangat miskin. Dalam bukunya, Pramoedya menjelaskan bahwa Kartini berkata, “Keahlian mereka tidak boleh dibiarkan merana”.
Kartini rajin mempromosikan ukiran mereka dengan cara memberikannya kepada kawan-kawan Belanda Kartini yang berada di Semarang, Batavia hingga yang bertempat di Belanda. Kartini juga sering menulis di surat kabar yang ada di hindia Belanda tentang keindahan seni ukir Jepara, sehingga pada tahun 1899 Kartini berhasil membangun hubungan dagang dengan Oost en West, sebuah lembaga perdagangan yang dipimpin oleh seorang wanita Belanda bernama Ny. N. Van Zuylen Trompt.
Keberpihakan Kartini terhadap kemandirian ekonomi masyarakat sipil, sangat bertentangan dengan cara pandang rezim militeristik-kapitalis yang memiliki hubungan kompleks dan saling mempengaruhi. Negara-negara kapitalis selalu bersaing satu sama lain untuk berebut pasar, sumber daya alam dan pengaruh di dunia. Dalam persaingan itu, kekuatan militer diperlukan.
Indonesia telah mengalami masa tersebut selama 32 tahun rezim militeristik-kapitalis memimpin. Richard Robinson dalam bukunya Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia (2012) menjelaskan bahwa kapitalisme berkembang pesat saat Soeharto berkuasa, sehingga suatu kelas kapitalis muncul dengan negara sebagai katalisatornya.
Kelas kapitalis yang muncul itu kemudian menjadi kelas yang penting dalam ekonomi politik Indonesia. Saking perkasanya, negara pun nyaris dicengkeram dan dikuasai oleh “kelas” tersebut. Penguasa (militer) dan pengusaha telah menyatu dan melahirkan keluarga-keluarga birokratis – konglomeratis yang posisinya ditentukan oleh suatu sistem patronase yang sangat korup dan tersentralisasi dibawah rezim Soeharto.
Terciptanya rezim korup tersebut tentu saja berimbas kepada masyarakat sipil kelas menengah kebawah. Kesejahteraan masyarakat sipil yang didambakan oleh Kartini, harus menghadapi rintangan besar di era Soeharto.
Jalan Panjang Para Pewaris Kartini
Cita-cita Kartini untuk membangun suatu sistem sosial yang setara gender di Indonesia, sudah bisa kita rasakan saat ini. Banyaknya perempuan yang menjabat pada sektor publik menjadi salah satu indikator terwujudnya cita-cita Kartini. Tidak jarang kita temui para cendekiawan, tokoh agama hingga pimpinan daerah merupakan jabatan yang saat ini lazim ditemukan.
Ide dan perjuangan Kartini yang merupakan penggerak awal keadilan gender di Indonesia, agaknya perlu digali dan dimaknai kembali bagi para penerusnya. Kita pernah mengalami masa gemilang ketika gerakan perempuan menjadi salah satu puzzle kemerdekaan Indonesia.
Kita juga pernah mengalami masa-masa kelam pada era orde baru dibawah bayang-bayang militer, dimana perempuan mengalami kemiskinan struktural, keterbelakangan berpikir, banyaknya kasus pelecehan seksual dari sesama sipil maupun aparat dan stereotyping yang sangat mengintimidasi peran perempuan.
Saat ini, gejala awal untuk membuka kembali luka lama orba telah terlihat; UU TNI yang disahkan membuat tentara masuk ke kampus, penegakan hukum yang tebang pilih, maraknya kasus pelecehan seksual di berbagai instansi yang tidak jelas penyelesaian hukumnya, hingga intimidasi siber yang dilakukan oleh para aktivis media sosial yang berupa; penggiringan buzzer, peretasan hingga doxing yang mereka terima.
Kartini, bukan hanya terlahir di era kolonialisme. Semangat Kartini mengalir dari generasi ke generasi kepada mereka yang sadar bahwa penjajahan pasti dimulai ketika suatu negara mulai memusuhi rakyatnya.
Misalnya, korupsi dengan nilai fantastis, praktek nepotisme dalam pemerintahan hingga kelesuan rupiah yang menyebabkan tingginya harga bahan pokok serta badai PHK yang terjadi bersamaan dengan sempitnya lapangan pekerjaan.
Indonesia sebentar lagi genap berusia 80. Indonesia hari ini memiliki akses keterbukaan pengetahuan yang telah terbuka lebar. Media sosial yang riuh sudah seharusnya diisi oleh para pewaris pikiran-pikiran Kartini. Ide-ide keberpihakan Kartini sudah seharusnya diinterpretasikan menjadi sebuah gerakan yang berdampak pada masyarakat sipil.
Dengan disahkannya UU TNI tahun ini, jalan panjang menuju cita-cita Kartini agaknya akan menjadi semakin berat. Namun, pesan Kartini yang selalu harus kita ingat bahwa; “Tidak ada perjuangan yang sia-sia, tidak ada kegelapan yang abadi”. Selamat Hari Kartini.