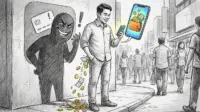Berbicara mengenai isu lingkungan, Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah organik dan pencemaran. Setiap hari, rumah tangga, pasar tradisional, hingga industri makanan menghasilkan limbah organik dalam jumlah besar yang pada akhirnya hanya menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Limbah tersebut tidak hanya mencemari udara dan tanah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Ironisnya, sebagian besar dari limbah ini sejatinya masih memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan kembali.
Salah satu contoh limbah organik yang kerap dianggap tak berguna adalah daun ubi. Di berbagai wilayah, terutama di daerah pertanian, daun ubi sering kali dibuang begitu saja usai panen. Padahal, bagian tanaman ini dapat menjadi bahan dasar ecoenzym, sebuah cairan hasil fermentasi yang memiliki banyak manfaat bagi lingkungan.
Berangkat dari keprihatinan terhadap persoalan tersebut, sekelompok mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG Surabaya), di bawah bimbingan dosen Zida Wahyuddin, S.Pd., menggagas inisiatif pemanfaatan limbah daun ubi untuk dijadikan ecoenzym. Kegiatan ini mereka lakukan bersama petani ubi Cilembu di Desa Duyung, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Selama ini, diskusi terkait pengelolaan sampah lebih banyak terfokus pada plastik dan limbah anorganik. Padahal, kenyataannya, limbah organik seperti sisa makanan, daun, dan kulit buah justru menjadi komponen terbesar dalam timbunan sampah rumah tangga di Indonesia. Dalam konteks inilah, produksi ecoenzym berbasis daun ubi menjadi solusi konkret yang ekonomis, edukatif, dan ramah lingkungan.
Ecoenzym sendiri merupakan cairan yang dihasilkan dari fermentasi bahan organik seperti sisa buah, sayuran, atau daun dengan campuran gula merah dan air, lalu disimpan dalam wadah tertutup selama kurang lebih tiga bulan.
Hasilnya adalah cairan kaya enzim dan mikroorganisme baik, yang dapat digunakan sebagai pembersih alami, pupuk cair organik, hingga untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki kualitas udara.
Proses pembuatannya pun relatif sederhana. Daun ubi yang telah dicincang halus dicampur dengan gula merah dan air bersih, lalu difermentasi dalam wadah tertutup. Selama proses ini, mikroorganisme bekerja mengurai bahan organik sehingga menghasilkan larutan kaya manfaat. Inilah bentuk teknologi sederhana berbasis kearifan lokal yang bisa dengan mudah diaplikasikan di tingkat desa.
Pemberdayaan masyarakat berbasis ecoenzym yang digagas mahasiswa UNTAG ini telah mulai diperkenalkan kepada warga Desa Duyung. Warga tidak hanya diajak mengenal manfaat ecoenzym, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembuatannya.
Hasil fermentasi kemudian digunakan untuk menyuburkan lahan pertanian dan membersihkan lingkungan sekitar. Dampak positifnya tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga ekonomi dan edukatif.
Salah satu poin penting dari kegiatan ini adalah perubahan cara pandang masyarakat terhadap sampah. Warga mulai menyadari bahwa limbah organik bukan semata-mata sampah, tetapi merupakan potensi sumber daya yang bisa diolah dan dimanfaatkan kembali. Ini menjadi bagian dari pendidikan lingkungan hidup yang selama ini masih kurang dijangkau di tingkat akar rumput.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana potensi gerakan ini di masa depan? Jawabannya tentu terletak pada konsistensi pelaksanaan, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan dari pemerintah dan kalangan akademisi. Bila digarap dengan serius dan berkelanjutan, inisiatif seperti ini dapat menjadi solusi lokal terhadap tantangan global seperti perubahan iklim.
Sebagaimana pernah dikatakan oleh Thomas L. Friedman bahwa masa depan ekonomi akan dimenangkan oleh negara-negara yang “hijau”, maka Indonesia punya harapan besar jika mampu membumikan inovasi-inovasi berbasis lingkungan seperti ini. Daun ubi yang selama ini dianggap remeh justru bisa menjadi simbol perlawanan terhadap krisis ekologis.
Dengan edukasi yang tepat dan efisiensi dalam pelaksanaan, tidak menutup kemungkinan bahwa ecoenzym dari daun ubi bisa menjadi gerakan nasional. Gerakan ini berpeluang besar mendorong perubahan budaya masyarakat: dari budaya membuang menjadi budaya mengolah.
Semoga inisiatif mahasiswa KKN Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini dapat menjadi contoh inspiratif bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia untuk memulai langkah kecil yang berdampak besar bagi kelestarian lingkungan.