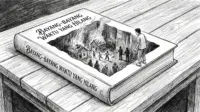Film “Lyora: Penantian Buah Hati” bukan hanya sebuah kisah tentang perjuangan mendapatkan anak, melainkan refleksi mendalam tentang bagaimana masyarakat memandang perempuan dan peran keibuan.
Diangkat dari kisah nyata jurnalis Meutya Hafid, film ini menggugah kesadaran kita tentang luka yang sering tersembunyi di balik pertanyaan sederhana, “Kapan punya anak?” Pertanyaan yang tampak ringan itu, ternyata dapat menjadi sumber tekanan sosial yang menggerus harga diri dan kesejahteraan psikologis seorang perempuan.
Film ini secara cermat mengupas dimensi sosial dan emosional dari perjuangan seorang perempuan yang menghadapi stigma infertilitas. Melalui tokoh Lyora, penonton diajak menyelami bagaimana pandangan masyarakat bisa membentuk cara seorang perempuan memandang dirinya sendiri.
Berdasarkan teori stigma dari Erving Goffman (1963), Lyora kerap merasa dirinya berbeda dan gagal karena belum memiliki anak. Ia bukan hanya menanggung tekanan eksternal dari masyarakat, tetapi juga tekanan internal yang lahir dari rasa bersalah dan rendah diri.
Pergulatan batin Lyora semakin nyata saat film ini menyoroti teori perbandingan sosial dari Leon Festinger (1954). Dalam berbagai adegan, Lyora kerap membandingkan dirinya dengan teman-teman yang sudah menjadi ibu.
Pemandangan sederhana seperti ibu-ibu yang bermain dengan anaknya mampu menjadi pemicu rasa kehilangan dan ketidakpuasan. Film ini berhasil menampilkan sisi manusiawi Lyora tanpa terjebak dalam melodrama, membuat penonton ikut merasakan beban yang ia tanggung.
Lebih jauh, konflik Lyora memperlihatkan kompleksitas identitas sosial perempuan. Berdasarkan teori identitas sosial dari Tajfel dan Turner (1979), Lyora hidup di tengah tarik-menarik antara identitas personalnya sebagai perempuan mandiri dan identitas sosialnya sebagai istri dalam budaya patriarkal.
Ia berada di persimpangan: di satu sisi ia sukses secara profesional, namun di sisi lain terus dipandang kurang sempurna karena belum menjadi ibu. Inilah dilema yang dialami banyak perempuan modern Indonesia berjuang menyeimbangkan antara ekspektasi sosial dan kebahagiaan pribadi.
Namun, film ini tak berhenti pada kesedihan. Ia juga memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan empati dan dukungan sosial. Sejalan dengan teori empati dari Gordon Allport (1954), perubahan dalam dinamika hubungan Lyora dengan orang-orang di sekitarnya menjadi titik balik yang penting. Ketika empati mulai menggantikan penilaian, ketika kehangatan mulai menggantikan tekanan, Lyora menemukan kekuatan untuk berdamai dengan dirinya sendiri.
Relevansi film ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan data WHO (2023) yang mencatat bahwa 10–15% pasangan usia subur di Indonesia mengalami infertilitas. Angka ini menunjukkan bahwa kisah Lyora bukan sekadar kisah individu, melainkan cerminan realitas sosial yang dialami banyak pasangan. Di tengah tuntutan modernitas dan budaya patriarki yang masih kental, perempuan kerap menjadi pihak yang paling disalahkan.
“Lyora: Penantian Buah Hati” menjadi film yang tidak hanya mengundang air mata, tetapi juga membuka ruang refleksi. Ia mengingatkan kita bahwa nilai seorang perempuan tidak terletak pada fungsi biologisnya, melainkan pada kemanusiaan dan kontribusinya.
Film ini layak diapresiasi karena mampu menyoroti isu sosial dengan pendekatan psikologis yang tajam dan menyentuh hati. Pada akhirnya, Lyora mengajarkan bahwa perjalanan menjadi utuh sebagai manusia bukanlah tentang memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan tentang menemukan makna diri yang sesungguhnya.