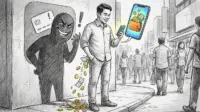Setiap kali para pemangku kebijakan berbicara tentang masa depan pendidikan Indonesia, mereka nyaris tak pernah lupa menyisipkan frasa “generasi berkarakter.” Kata-kata seperti “akhlak,” “etika,” hingga “nilai-nilai kebangsaan” seakan menjadi bumbu wajib dalam setiap pidato pendidikan.
Namun, ketika semua nilai luhur itu harus diterjemahkan ke dalam angka, rapor, atau sistem penilaian nasional, maknanya kerap menjadi kabur dan kehilangan esensi.
Asesmen afektif, yakni penilaian terhadap sikap, nilai, dan karakter peserta didik, hingga hari ini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ia tercantum dalam kurikulum, diajarkan di ruang kelas, namun tidak memiliki alat ukur yang sistematis, konsisten, dan berkelanjutan.
Kita masih sering melihat kasus peserta didik yang terlibat dalam perundungan, pornografi, tindakan kekerasan, hingga ujaran kebencian. Jika ini masih terjadi, pertanyaannya: sudahkah tujuan pendidikan karakter yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah benar-benar tercapai?
Karakter yang Didamba, Tapi Tak Pernah Terukur
Pendidikan karakter semestinya menjadi inti, bukan pelengkap dari proses pendidikan. Namun kenyataan berkata lain. Sistem pendidikan kita cenderung menitikberatkan pada aspek kognitif semata—pengetahuan yang diukur melalui ujian pilihan ganda, hafalan, dan tugas-tugas akademik. Sementara itu, nilai-nilai afektif seperti kejujuran, empati, tanggung jawab, dan kerja sama hanya dicatat secara subjektif dan kerap bergantung pada intuisi guru.
Bukan salah guru semata. Mereka pun adalah korban dari sistem yang tidak memberi mereka alat ukur konkret untuk melakukan penilaian afektif. Yang tersedia hanyalah lembar observasi sederhana atau catatan mingguan.
Mungkinkah karakter yang terbentuk dari proses panjang itu diukur hanya dengan kategori “baik,” “cukup,” atau “perlu pembinaan”? Bahkan sering kali, indikator penilaian yang digunakan tidak mencerminkan realitas perilaku siswa di luar sekolah.
Masalah ini makin pelik karena sebagian besar perilaku anak justru terbentuk di luar ruang kelas. Mereka belajar dari rumah, lingkungan pergaulan, bahkan media sosial. Namun, penilaian afektif hanya berlaku saat jam pelajaran berlangsung atau ketika guru hadir. Maka tak heran bila asesmen ini sering kali gagal merefleksikan kondisi sebenarnya.
Peserta didik bisa terlihat sopan di kelas, tapi siapa yang tahu jika di rumah ia membentak orang tua, atau di dunia maya ia menjadi pelaku perundungan digital? Sekolah hanya melihat sebagian kecil dari dunia mereka.
Tantangan di Lapangan: Dari Guru Sampai Keluarga
Salah satu hambatan utama asesmen afektif adalah terbatasnya waktu dan tenaga guru untuk mengenali setiap siswa secara mendalam. Dalam satu kelas yang berisi 30 hingga 40 peserta didik, guru juga dibebani tanggung jawab administratif seperti membuat perangkat ajar hingga laporan daring. Dalam kondisi seperti ini, perhatian personal menjadi barang mewah.
Belum lagi bicara soal kompetensi guru dalam menilai aspek afektif. Banyak dari mereka belum mendapat pelatihan untuk membaca ekspresi emosional, mencatat perubahan sikap, atau menyusun portofolio karakter.
Di sisi lain, keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter juga masih minim. Banyak yang masih berpandangan bahwa pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah. Padahal, karakter anak lebih banyak dibentuk dari keluarga dan lingkungan sosialnya.
Tanpa sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, penilaian karakter akan selalu setengah matang. Terlebih lagi, asesmen nasional seperti ANBK, AKM, atau PISA belum menyentuh ranah afektif secara serius. Fokus utama masih berkutat pada literasi, numerasi, dan sains. Maka, jangan heran jika anak yang terbiasa mencontek atau membully tetap bisa lulus dengan predikat “sangat baik.”
Solusi Menuju Asesmen Afektif yang Bermakna
Apakah kita akan terus menyerah pada kesulitan dalam mengukur karakter? Tentu tidak. Ada langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memperbaiki sistem ini.
Pertama, mengembangkan instrumen penilaian afektif berbasis narasi dan portofolio. Karakter tidak dapat diringkas dalam angka. Penilaian berbentuk narasi seperti jurnal harian siswa, catatan reflektif, atau portofolio moral dapat memberikan gambaran utuh tentang perkembangan kepribadian mereka. Meskipun memakan waktu, pendekatan ini jauh lebih bermakna.
Kedua, melibatkan pihak lain dalam pengamatan dan pembinaan karakter. Sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu ada sinergi antara guru, orang tua, dan masyarakat. Orang tua bisa diajak aktif melalui laporan bulanan atau forum komunikasi. Bahkan, tokoh masyarakat seperti ketua RT atau pengurus karang taruna dapat turut memberikan masukan tentang sikap anak-anak di lingkungannya.
Ketiga, memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan perkembangan karakter secara berkelanjutan. Platform digital dapat dibuat untuk mencatat perilaku siswa, baik positif maupun negatif, dalam jangka panjang. Sistem ini bisa menjadi media kolaboratif antara guru, wali kelas, dan orang tua dalam memantau perkembangan afektif peserta didik secara komprehensif.
Keempat, pemerintah harus memberikan pelatihan khusus tentang asesmen afektif bagi guru. Materi pelatihan bisa mencakup teknik observasi perilaku, komunikasi empatik, hingga pengelolaan portofolio. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, guru dapat melakukan penilaian secara objektif dan berkelanjutan.
Kelima, membangun budaya sekolah yang menumbuhkan pendidikan karakter. Lingkungan sekolah harus mendukung nilai-nilai luhur dalam setiap aktivitas. Guru dan tenaga pendidik harus menjadi teladan, sementara siswa diajak untuk hidup dalam nilai-nilai kebaikan setiap hari. Menghargai siswa bukan hanya karena nilai akademik, tetapi juga karena integritas dan etika, harus menjadi bagian dari tradisi pendidikan kita.
Saatnya Pendidikan Karakter Tidak Hanya Menjadi Retorika
Jika kita sungguh ingin melahirkan generasi yang bukan hanya cerdas, tapi juga bermoral, maka asesmen afektif harus mendapat tempat utama. Ia tidak bisa terus-menerus menjadi pelengkap administratif atau sekadar pengisi kolom rapor.
Pendidikan yang gagal mengukur karakter sejatinya adalah pendidikan yang gagal membentuk manusia seutuhnya. Sudah waktunya kita berhenti berpura-pura bahwa sistem kita baik-baik saja. Pendidikan karakter bukanlah slogan belaka, melainkan sebuah komitmen untuk membentuk generasi yang tahu membedakan mana yang benar dan mana yang baik, bahkan saat tidak ada yang menyaksikannya.