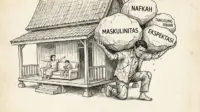Hukum Islam (syariah) berkembang seiring perjalanan sejarah umat Islam, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Pada masa Nabi Muhammad SAW (610–632 M), hukum Islam bersumber langsung dari wahyu Allah yang tertuang dalam Al-Qur’an serta penjelasan Nabi melalui sunnah. Hukum pada masa ini tidak hanya mengatur aspek ritual keagamaan, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan pidana, seperti zakat, puasa, dan haji.
Setelah wafatnya Nabi, masa Khulafaur Rasyidin (11–40 H) menjadi periode penting dalam pengembangan hukum Islam. Para sahabat menghadapi berbagai persoalan baru yang membutuhkan solusi hukum, sehingga muncullah metode ijtihad dan musyawarah sebagai cara pengambilan keputusan hukum.
Selanjutnya, pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, hukum Islam mengalami perkembangan pesat dengan kemunculan berbagai mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali) yang masing-masing memiliki pendekatan penafsiran tersendiri terhadap sumber-sumber hukum Islam.
Pada era Abbasiyah (750–1258 M), terjadi kodifikasi besar-besaran terhadap ilmu fikih dan hadis sehingga hukum Islam menjadi semakin sistematis dan komprehensif. Modernisasi hukum Islam mulai terasa pada abad ke-19, ketika dunia Islam menghadapi pengaruh kolonialisme Barat serta tuntutan reformasi sosial dan hukum. Banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, mulai mengadaptasi hukum Islam agar tetap relevan dengan konteks zaman serta sistem hukum nasional yang berlaku.
Di Indonesia, masuknya Islam merupakan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama perdagangan maritim. Ada beberapa teori utama tentang asal-usul masuknya Islam ke Indonesia. Salah satunya adalah teori Gujarat, yang menyatakan bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, pada abad ke-7 M.
Bukti pendukungnya adalah batu nisan Sultan Malik al-Saleh di Aceh yang bergaya Gujarat serta kemiripan mazhab Syafi’i di kedua wilayah tersebut. Namun, teori ini mendapat kritik karena terlalu mengandalkan bukti fisik dan kurang memperhatikan peran masyarakat lokal dalam penyebaran Islam.
Teori Makkah atau Arab menyebut bahwa ajaran Islam dibawa oleh jamaah haji dan peziarah dari Makkah yang kembali ke Nusantara. Pandangan ini didukung oleh sejarawan seperti Van Leur, T.W. Arnold, dan Buya Hamka.
Sementara itu, teori Persia menunjukkan adanya pengaruh pedagang Persia melalui jalur perdagangan dan budaya, seperti tradisi Tabut di Sumatera Barat yang mirip dengan perayaan Syiah di Persia. Ada juga teori Tiongkok, yang menyebutkan bahwa pedagang Muslim dari Tiongkok turut andil dalam penyebaran Islam di Nusantara.
Bukti sejarah menunjukkan bahwa Islam telah hadir di Indonesia sejak abad ke-7. Namun, pengaruhnya semakin nyata pada abad ke-13 seiring berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh dan Demak di Jawa. Proses Islamisasi di Indonesia berlangsung damai dan akulturatif, sehingga hukum Islam dapat diterima oleh masyarakat yang sebelumnya menganut Hindu-Buddha.
Pada masa kerajaan Islam, hukum Islam menjadi dasar pemerintahan dan kehidupan sosial. Namun, pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam mengalami kemunduran. Awalnya Belanda bersikap kompromis, tetapi kemudian menerapkan politik pembenturan antara hukum Islam dan hukum adat untuk menggantinya dengan hukum Belanda.
Setelah kemerdekaan Indonesia, hukum Islam kembali mendapatkan tempat melalui pembentukan lembaga peradilan agama dan pengakuan terhadap hukum keluarga Islam. Hal ini dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri di bidang tertentu seperti perkawinan, waris, dan wakaf.
Era Reformasi membawa angin segar bagi hukum Islam di Indonesia. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 membuka peluang hadirnya peraturan daerah berbasis syariah, terutama di daerah-daerah dengan karakteristik khusus seperti Aceh. Di Aceh, hukum Islam bahkan diakomodasi dalam bentuk Qanun yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai prinsip-prinsip syariah.
Sumber utama hukum Islam tetap berakar pada empat pokok ajaran: Al-Qur’an, sebagai kitab suci umat Islam yang menjadi landasan utama dalam segala aspek hukum; Sunnah (hadis), sebagai penjelas Al-Qur’an melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW; Ijma’, yaitu kesepakatan para ulama terhadap suatu permasalahan hukum; serta Qiyas, yaitu analogi hukum berdasarkan kasus serupa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an atau sunnah.
Beberapa mazhab seperti Maliki juga mengakui praktik masyarakat Madinah (amal ahl al-Madinah) sebagai sumber hukum karena Madinah dianggap sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam dan tempat tinggal Nabi serta para sahabat setelah hijrah. Dalam praktiknya, hukum Islam mengatur hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah (ritual keagamaan) maupun muamalah (hubungan sosial, ekonomi, dan hukum pidana).
Dapat disimpulkan bahwa kekuatan dan relevansi hukum Islam sejak awal perkembangannya hingga eksistensinya saat ini di Indonesia terletak pada kemampuannya dalam beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilainya.
Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum nasional, hukum Islam berpeluang terus berkembang sebagai bagian penting dari sistem hukum Indonesia yang plural dan inklusif.