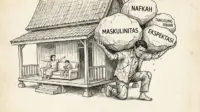Kita hidup di zaman yang aneh. Kesunyian telah digantikan suara notifikasi. Makna telah tunduk pada tuntutan citra. Arena notifikasi ini serba tontonan. Buku kehilangan martabatnya. Seharusnya, buku adalah gudang makna. Ia adalah ruang pergulatan sunyi.
Kini, buku direduksi menjadi properti estetika belaka. Ia hanya menjadi latar foto yang dipamerkan di story atau feed. Membaca kehilangan substansinya. Ia berubah menjadi bagian dari branding diri. Ini tak ubahnya kopi kekinian atau outfit minimalis. Membaca menjadi investasi simbolik untuk konsumsi publik.
Pergeseran fungsi buku ini membawa kita pada pertanyaan mendasar: mengapa validasi visual kini lebih dominan? Mengapa esensi intelektual menjadi nomor dua? Fenomena ini adalah cerminan dari Masyarakat Tontonan (La société du spectacle) oleh Guy Debord.
Dalam masyarakat ini, pengalaman otentik, pergulatan batin saat membaca, digantikan “representasi” citra. Membaca yang sejati dipertukarkan dengan tontonan membaca. Keheningan intim diganti hitungan likes. Ia diganti bayangan, “Kalau aku foto bagian ini, pasti keren buat di-post.” Jelas, kita seakan tak lagi mencari makna. Kita hanya mencari validasi visual.
Dari Makna Pribadi Menjadi Modal Sosial
Reduksi membaca menjadi tontonan adalah tragedi budaya digital. Jika dulu orang menulis catatan kaki di buku untuk diri sendiri, kini orang menambahkan caption aesthetic dengan kutipan dangkal demi audiens. Catatan kaki adalah proses belajar. Caption adalah pertunjukan. Perbedaan mendasarnya terletak pada tujuan: proses internal atau persetujuan eksternal.
Secara sosiologis, hal ini sangat selaras dengan konsep Modal Budaya (Cultural Capital) dari Pierre Bourdieu. Buku yang dipamerkan adalah sebuah penanda. Ia adalah aset “non-finansial” yang digunakan untuk menegaskan status sosial.
Tindakan memamerkan buku tertentu, misalnya karya filsafat, sastra klasik, atau teori kritis, adalah kode sosial yang dikirimkan kepada audiens: “Aku intelektual, aku berwawasan, aku berbeda dari kalian yang hanya sibuk menonton sinetron”.
Di sini, buku berfungsi sebagai alat diskriminasi sosial. Ia memposisikan pemegangnya pada hierarki budaya yang lebih tinggi. Nilai buku tidak lagi terletak pada isinya, tetapi pada kemampuan simboliknya untuk memperkaya citra seseorang. Membaca berubah fungsi. Dari upaya mencari makna, ia menjadi investasi simbolik untuk mobilitas status.
Tindakan memamerkan modal budaya ini memiliki akar psikologis yang dalam. Penelitian ilmiah mendukung bahwa perilaku flexing, termasuk flexing intelektual, sering didorong kebutuhan mengisi kekosongan identitas.
Ini adalah upaya mencari validasi eksternal untuk menopang citra diri. Hal ini menegaskan, buku tidak dibaca untuk membuka cakrawala. Buku dipakai untuk menutup kekosongan itu. Maka, makna menjadi tidak penting. Yang penting adalah engagement terpenuhi. Di sini kita terjebak pada ilusi intelektual. Kita merasa otomatis menjadi pembaca yang baik hanya karena memamerkan buku. Buku menjadi topeng modernitas. Ia dipakai bukan untuk memahami dunia. Ia dipakai untuk menutupi.
Performativitas dan Kematian Proses
Ilusi ini terjadi karena adanya reduksi total pada proses membaca itu sendiri. Para akademisi menyebutnya “Performative Reading“. Ini adalah kecenderungan membaca demi tampilan publik. Erving Goffman menjelaskan fenomena ini melalui konsep Dramaturgi. Media sosial adalah panggung depan (front stage). Di sana kita mengelola kesan diri secara hati-hati. Kita menampilkan versi ideal.
Kita hanya menampilkan versi glamor. Misalnya, foto buku dengan filter warm tone. Kita memilih sudut terbaik. Kita mengatur pencahayaan. Kita menyertakan properti pendukung seperti kopi atau jendela hujan.
Ini adalah manajemen kesan yang cermat. Namun, makna bekerja dalam ketidakromantisan di panggung belakang (back stage). Itu adalah perjuangan menahan kantuk di bab yang penuh teori. Itu adalah coretan frustrasi di margin. Itu adalah mengulang kalimat yang tidak dimengerti. Semua proses otentik ini disembunyikan. Kita hanya melihat hasil kurasi, bukan perjuangan kurasi itu sendiri.
Inilah ironi terbesarnya. Membaca sejati adalah kerja sunyi yang lama. Ia sering membosankan. Ia butuh kesabaran. Foto buku di story hanya menangkap sepersekian detik. Seringkali, foto itu justru menghapus prosesnya. Kita tidak melihat perjuangan intelektual. Kita hanya melihat kegiatan yang direkayasa sebagai romantis belaka.
Dominasi Medium dan Krisis Kognitif
Reduksi proses ini diperparah mekanisme platform digital. Filsuf Jean Baudrillard menyebut situasi ini Hiperrealitas. Citra diri sebagai “intelektual” yang berhasil diproduksi telah menjadi lebih meyakinkan daripada aktivitas membaca sebenarnya. Citra telah menggantikan substansi.
Lebih lanjut, Marshall McLuhan menyatakan media tidak hanya menyebarkan pesan, tetapi juga memijat jiwa dan otak penerimanya. Media sosial mendorong visualitas, kecepatan, dan fragmentasi. Medium buku mendorong linearitas dan perenungan.
Ketika membaca ditarik ke medium media sosial, bentuk (foto, likes, story) mulai mendominasi isi (makna buku). Ekonomi visibilitas ini memaksa refleksi pribadi diterjemahkan segera menjadi nilai yang dapat dibagikan (sharable value). Algoritma menghargai yang fotografis di atas yang introspektif.
Konsekuensi dominasi visual dan fragmentasi ini adalah hilangnya keheningan yang vital. Sherry Turkle dalam studinya memperingatkan bagaimana teknologi digital “mengikis dan mempengaruhi” ruang kesunyian yang dibutuhkan untuk perenungan. Dorongan untuk segera memposting merusak reflective lag yang dibutuhkan buku-buku mendalam. Aktivitas sunyi diganggu oleh kebutuhan akan validasi dari audiens.
Secara kognitif, ini menimbulkan masalah serius. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan multitasking digital memengaruhi kemampuan fokus dan perhatian. Otak menjadi terbiasa dengan asupan informasi yang terfragmentasi dan cepat. Akibatnya, kesulitan untuk fokus pada bab yang penuh teori dan kehilangan keheningan menjadi masalah kognitif nyata. Buku yang menuntut perhatian penuh terasa melelahkan.
Byung-Chul Han menambahkan dimensi filsafat sosial. Dalam kritiknya, ia menyoroti tuntutan untuk selalu tampil dan berkinerja dalam masyarakat modern. Transparansi mutlak menuntut setiap aspek kehidupan dilihat dan diukur. Pengetahuan dianggap metrik kinerja yang harus dilaporkan, memaksa kita memamerkan proses belajar.
Ini adalah tekanan kinerja intelektual yang menolak ruang hening. Membaca yang sesungguhnya, yang berantakan dan lambat, tidak dapat diukur. Ia tidak dapat di-upload. Dan bagi Byung-Chul Han, itulah yang disebut sebagai “Masyarakat Kinerja”. Masyarakat penuh tuntutan manipulasi dalam diri mereka.
Perlawanan dalam Kesunyian
Pertanyaan besarnya adalah: bagaimana kita mengembalikan martabat membaca? Bagaimana kita menolak menjadi sekadar penampil?
Kita harus kembali pada kesunyian yang jujur. Membaca tanpa perlu difoto. Membaca tanpa perlu filter. Membaca tanpa perlu merasa harus dilihat. Ini adalah proses belajar murni. Ini bukan proses membangun citra. Membaca sejati sering kali berantakan.
Ia melibatkan mencatat dengan tulisan miring. Ia melibatkan menggarisbawahi dengan stabilo murahan. Ia melibatkan mengulang kalimat yang tidak dimengerti. Justru dalam ketidakromantisan itulah makna bekerja. Ia masuk pelan-pelan. Ia menumbuhkan pemahaman. Ia mengubah cara kita memandang dunia.
Membaca sejati adalah bentuk perlawanan kecil di era digital. Kita menolak menjadi komoditas. Kita menolak menjadi sekadar data. Kita menolak mematuhi aturan platform yang mendahulukan kecepatan di atas kedalaman. Kita memilih kedalaman di atas likes. Kita memilih makna di atas story.
Membaca atau Difoto?
Pertanyaan untuk kita semua sangat sederhana: apakah kita benar-benar membaca, atau hanya difoto sedang membaca? Apakah kita membuka buku untuk memahami isinya, atau untuk membuka kamera?
Jika membaca hanya properti estetika, maka buku tak lebih dari wallpaper di layar ponsel kita. Padahal, buku bisa menjadi senjata. Ia bisa menjadi cermin. Ia bisa menjadi jendela ke dunia lain. Semua itu hanya mungkin jika kita membacanya penuh kesadaran. Bukan dengan kalkulasi sosial.
Kita perlu belajar malu. Malu ketika menata buku di rak hanya untuk latar belakang Zoom. Malu ketika membeli buku hanya demi foto. Malu ketika membaca hanya separuh halaman tapi merasa pantas memberi ulasan.
Membaca bukanlah pameran. Membaca adalah perjalanan. Pada akhirnya, yang lebih penting dari memperlihatkan bahwa kita membaca, adalah benar-benar membaca. Dan membagikan makna yang lahir darinya ke dalam kehidupan.
Penulis Buku Paradigma Pendidikan Profetik Kuntowijoyo: Problem, Pemikiran, dan Aktualisasi di Era Revolusi Industri 4.0.
Aktivitas menjadi Penikmat Surah di Gerakan Surah Buku (GSB). Salah satu Komunitas Literasi di Jogja, tepatnya di Asrama Aceh Sabena (Jalan Taman Siswa).